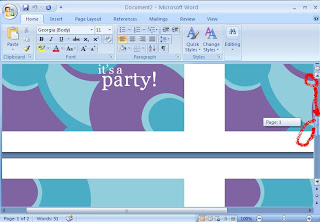ACEH
Artinya: Arab, China, Eropa, dan Hindia
Dari judul di atas, setidaknya ada tiga hal yang menjadi pertanyaan bagi kita yakni pertama, sejarah, perjuangan, dan bangsa Aceh. Tiga hal tersebut memang membutuhkan waktu yang lama untuk mengkaji atau mendiskusikannya. Sebab, sepengetahuan penulis, kajian tentang sejarah Aceh telah banyak ditulis baik itu oleh orang Aceh sendiri maupun orang luar. Misalnya, kajian H.M. Zainuddin,[1] Ibrahim Alfian,[2] Lee Kam Hing,[3] C. Snouck Hurgronje,[4] dan lain sebagainya.[5]
Karya-karya di atas, tentunya sudah pernah dibaca oleh kita semua. Karena itu, untuk menjelaskan sejarah perjuangan Aceh, nampaknya karya yang penulis kemukakan tersebut cukup membantu dalam memahami sejarah perjuangan bangsa Aceh. Apalagi, sekarang kondisi Aceh masih bergejolak. Karenanya, tujuan dari kajian kita pada bab ini adalah mencari titik-titik temu sejarah yang bisa dirakit kembali untuk perjuangan masyarakat Aceh. Dengan tujuan ini, diharapkan setiap rakyat Aceh punya kesadaran tentang sejarah yang tidak hanya untuk dijadikan bahan kebanggaan daerah, tapi juga bisa menciptakan sejarah yang pernah terjadi di tempoe doeloe. Dengan demikian, generasi yang sadar sejarah sangat diharapkan di era masa depan. Sebab, ketika sejarah tidak ditulis atau direduksi, maka sekian banyak kerugian yang diderita oleh suatu bangsa.[6]
Dalam konteks di atas, Taufik Abdullah menyatakan bahwa sejarah memang mempunyai arti ganda. Pertama, sejarah sebagai pengalaman empiris – sebagai sebagai peristiwa penting yang dilalui. Kedua, sejarah sebagai bagian dari kesadaran –ketika pengalaman itu telah diberi makna. Artinya, dari pengalaman empiris itu berbagai pesan dan pelajaran serta kebijaksanaan telah diambil.[7] Karena itu, Asvi Warman Adam berkesimpulan tentang fungsi sosial-politik dari sejarah tidak sama pada seluruh masyarakat di dunia. Ada yang berfungsi untuk mengkonsolidasikan persatuan dan kesatuan bangsa, ada pula yang bertujuan untuk menemukan jati diri suatu bangsa serta mencari “kebenaran” mengenai masa lampau, ada juga yang berperan untuk mencerdaskan warga negara.[8]
Dalam kerangka ini, kajian ini diajak untuk memahami sejarah perjuangan bangsa Aceh.[9] Sejarah sebagai konsolidasi yaitu dimana setiap kita menjadikan peristiwa masa lalu sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Aceh. Sejarah sebagai penemuan jati diri adalah sejarah yang menggambarkan bangsa Aceh sebagai salah satu bangsa yang pernah jaya di panggung dunia, yang pada gilirannya aspek ini membentuk jiwa yang mampu menatap ke depan bukan ke belakang sebagai romantisisme yang malah bukan menemukan jati diri akan tetapi lupa diri. Sejarah sebagai alat pencerdasan merupakan sejarah yang menjadikan setiap pembacanya mengerti dan belajar dari peristiwa tersebut bukan untuk mengulangi. Sebab, sejarah hanya berlaku untuk ruang dan waktu tertentu yang karenanya sejarah tidak untuk dikenang-kenang tapi bagaimana sejarah bisa memenangkan perjuangan.
Keberhasilan Bangsa Aceh Tempoe Doeloe
Mengungkapkan keberhasilan suatu bangsa –khususnya Aceh– dalam tinjauan sejarah bukan hal yang sulit. Sebab, Aceh merupakan salah satu kawasan di Nusantara yang beruntung yang sejarahnya banyak ditulis oleh para peneliti. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari karya-karya di atas yang menunjukkan bahwa sejarah Aceh masih dan akan terus ditulis. Namun, mengambil intisari mengapa perjuangan bangsa Aceh dahulu bisa berhasil bukan pekerjaan yang mudah. Sebab, jika sejarah ditulis oleh lawan, maka sejarah tersebut tidak akan terlepas dari bias penulis itu sendiri. Sebaliknya, sejarah yang ditulis oleh pribumi cenderung menonjolkan kelebihan tinimbang kekurangan. Untuk lebih jelasnya, maka pembahasan sub-bagian ini akan dibagi ke dalam tiga aspek yaitu, politik, ilmu pengetahuan, dan agama.
1. Politik
Dalam bagian politik, munculnya kerajaan Islam di Aceh merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh para generasi muda Aceh.[10] Secara kronologi, setidaknya ada lima kerajaan Islam di Aceh, yaitu Kerajaan Peureulak, Benua Tamiang, Kerajaan Islam Samudera Pasai, Kerajaan Islam Lamuri, dalam Kerajaan Islam Aceh.
Kerajaan Pereulak[11] merupakan kerajaan Islam pertama di Aceh, bahkan di Indonesia. H. M. Zainuddin mencatat bahwa Kerajaan Peureulak adalah lebih tua dari kerajaan Tumasik (Singapura) dan Bintan, juga jauh lebih tua dari kerajan Pasai dan Melaka, yang mungkin sebaya dengan kerajaan Aru dan Palembang (Sriwijaya), bahkan lebih tua dari kerajaan Majapahit di pulau Jawa.[12] Sistem ketatanegaraan, menurutnya, masih primitif atau rezim bangsa Melayu sekarang, yaitu kepala negerinya disebut Radjo/Radja, bawahannya disebut Kedjuren dan Penghulu, tidak seperti tradisi di Pasai, Pidie, dan Aceh Besar.[13]
Di samping kerajaan di atas, Kerajaan Benua Tamiang yang mula tidak beragama Islam,[14] kemudian setelah takluk ke Samudera dan memeluk agama Islam, maka oleh Sulthan Pasai diangkatlah raja lain yang bernama Radja Muda Sedia, pengganti Radja Dinok yang tewas dalam peperangan melawan tentera Samudra Pasai.[15]
Corak pemerintahan kerajaan ini disebutkan ber “Balai” dengan susunannya sebagai berikut: pertama, Raja dibantu oleh seorang Mangkubumi yang mempunyai tugas sehari-hari mengawasi jalannya pemerintahan dan ia bertanggung jawab kepada raja (pada waktu Raja Muda Sedia, mangkubuminya ialah: Muda Sedinu). Pertama, untuk mengawasi jalannya pelaksanaan hukum oleh pemerintah atau lembaga-lembaga penegak hukum yang dibentuk, diangkat pula seorang Qadhi Besar. Di Tingkat pemerintah daerah terdapat pula; a) Datuk-Datuk Besar yang memimpin daerah-daerah kedatuan; b) Datuk-Datuk Delapan Suku yang memimpin daerah-daerah suku perkauman; c) Raja-Raja Imam yang memimpin di daerah-daerah dan sekaligus juga bertindak sebagai sebagai penegak hukum di daerahnya.[16] Kerajaan ini pernah diserang pada sekitar tahun 1351 M., oleh kerajaan Majapahit.
Lebih lanjut, kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Islam Samudera Pasai. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-XI M. atau tepatnya pada tahun 1042 (433 H). Dan sebagai pendiri serta Sulthan yang pertama dari kerajaan ini adalah Maharaja Mahmud Syah, yang memerintah pada tahun 433-470, atau bertepatan dengan tahun 1042-1078 M.[17] Untuk mengambarkan tentang kerajaan ini, laporan Muhammad Ibrahim dan Rusdi Sufi nampaknya layak untuk disebutkan di sini:
Samudra Pasai adalah kerajaan yang bercorak Islam dan sebagai pemimpin tertinggi kerajaan berada di tangan Sulthan yang biasanya memerintah secara turun temurun. … di samping terdapat Sulthan sebagai pimpian kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti Menteri Besar (Perdana Menteri atau Orang Kaya Besar), Seorang Bendahara, seorang Komandan Militer atau Penglima Angkatan Laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris Kerajaan, seorang Kepala Mahkamah Agama yang dinamakan Qadi, dan beberapa orang Syahbandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para Syanbandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara Sulthan dan pedagang-pedagang asing.[18]
Sebagai bukti kemegahan kerajaan ini, kedatangan satu Musafir dari Timur Tengah dapat dijadikan sebagai data sejarah yang tidak dapat diabaikan, yakni Ibn Battutah. Ibnu Bathuthah datang ke Aceh pada 1345. Sedangkan yang menjadi tempat tujuan Ibn Bathuthah adalah Kerajaan Samudera Pasai. Ketika Ibn Bathuthah singgah di Pasai selama lima belas hari dalam tahun 746/1345, menyaksikan Islam aliran Sunni telah berkembang pesat dan madzhab yang dianut Syafi‘i. Kehidupan kerajaan bergaya Persia. Diceritakan pula bahwa di antara orang-orang besar kerajaan yang menjadi anggota majelis sultan termasuk Amir Daulah yang berasal dari Delhi, Qadli Amir Said dari Syiraz dan ahli hukum Tajuddin dari Isfahan. Ibn Bathuthah melaporkan juga bahwa banyak orang besar kerajaan pernah bertemu dengannya di Delhi.[19] Ibnu Di Bathuthah juga melaporkan perjalanannya mengatakan bahwa dalam sebuah pengertian politis, Samudera adalah pos luar yang paling akhir dari Dar al-Islam. Sekalipun kota-kota lainnya di sebelah Selatan sepanjang pantai Sumatra telah mengembangkan dengan suburnya permukiman-permukiman komersial, tidak ada negara Muslim merdeka yang diketahui eksistensinya dimana pun di sebelah Timur Samudera sebelum pertengahan abad keempat belas.[20] Di Samudera Pasai bertemu dengan salah seorang perwira tinggi militer, yang ternyata sudah dikenalnya. Orang itu pernah berpergian ke Delhi beberapa tahun sebelumnya dalam rangka misi diplomatik bagi Samudera.[21]
Setelah Kerajaan Samudera Pasai di Aceh tepatnya di Pidie ditemukan Kerajaan Islam Lamuri. Meski masih simpang siur, kabar tentang kerajaan ini, berdasarkan penulis-penulis luar, kerajaan Lamuri sudah disebut-sebut oleh berita-berita Arab sejak pertengahan abad ke IX M. Seperti juga kerajaan Islam Sumadra Pasai yang berpola maritim dan Islam, maka kerajaan Lamuri yang juga hampir berpola sama tentunya juga mempunyai sistem dan lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan kerajaan Islam Samudra Pasai.[22]
Terakhir, kerajaan Islam yang sampai sekarang masih dikaji adalah Kerajaan Islam Aceh. Pusat Kerajaan Aceh itu di Banda Aceh atau di Kutaraja sekarang ini yang mulai didirikan pada abd ke XV. Pada mulanya pusat pemerintahan Aceh terletak di satu tempat yang dinamakan kampung Ramni dan dipindahkan ke Darul Kamal oleh Sultan Alaudin Inayat Johan Syah (1408-1465) Kemudian memerintah Sulthan Muzaffar Syah (1465-1497. Beliaulah yang membangun kota Aceh Darussalam.[23]
Dari paparan di atas, yang ingin dikatakan bahwa bangsa Aceh telah lama menjadi bagian tersendiri dari kepulauan Nusantara. Walaupun demikian, jika data historis ini ditampilkan lagi sekarang, apakah bangsa Aceh akan bangkit seperti dulu lagi. Atau, sebaliknya justru malah mengalami kemunduran yang lebih parah dari sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pada bagian selanjutnya akan diulas tentang perkembangan ilmu pengetahuan di Aceh. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk membandingkan semangat pencarian ilmu tempoe doeloe dengan sekarang.
2. Ilmu Pengetahuan
Sayang memang, daerah Aceh sekarang menjadi propinsi terbelakang dalam bidang pendidikan. Daerah ini dulunya menjadi tempat mencari ilmu pengetahuan, sekarang malah sebaliknya, dari Aceh banyak yang mencari ilmu ke luar daerah yang pada gilirannya mutu pendidikan di daerah semakin menurun drastis. Bagi kita, khsusunya penulis, pendidikan adalah bentuk perjuangan total masa sekarang dan yang akan datang di Aceh.
Bangsa Aceh telah lama menjadi pusat pengkajian ilmu pengetahuan, khususnya studi Islam (islamic studies). Hampir setiap Raja di Aceh didampingi oleh para alim ulama. Di samping itu, lembaga pendidikan dayah[24] juga dapat ditemui di hampir seluruh daerah Aceh. Dayah di Aceh berfungsi 1) sebagai pusat belajar agama; (2) benteng terhadap kekuatan melawan penetrasi penjajah; (3) agen pembangunan; (4) sekolah bagi masyarakat.[25]
Oleh karena itu, tidak heran jika lembaga ini di Aceh menjadi pusat penggerak rakyat dalam berbagai bidang. Sebagai pusat belajar agama, dayah telah mendidik para calon ulama yang sampai sekarang masih dapat dilihat ditengah-tengah masyarakat. Menurut sejarah, para ulama yang datang dari Timur Tengah mengajarkan ilmu agama Islam di dayah-dayah. Atau, para teungku dayah pernah belajar pada seorang alim ulama dari Timur Tengah. Sebagai benteng pertahanan, dayah telah menoreh catatan sejarah tersendiri dalam lintasan berbagai peristiwa di Aceh. Bahkan pada waktu Kesultanan Aceh diserang Belanda, para ulama dengan gigih bertahan.[26]
Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dayah memegang peran yang cukup signifikan di Aceh. Jadi, jangan heran, jika sekarang ulama dan dayah di Aceh sering menjadi basis pertahanan Gerakan Acheh Merdeka. Hemat penulis, mereka mencontoh sejarah tempoe doeloe.
Selain dayah, di Aceh juga sangat terkenal dengan ulama yang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, khususnya Islam. Nama seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Abdur Rauf Singkeli, Nurdin Al-Raniri merupakan ulama yang sangat produktif menulis.[27] Melalui karya-karya mereka, Aceh dikenal sebagai tempat untuk mencari ilmu pengetahuan. Syekh Burhanuddin dari Ulakan, Pariaman adalah salah seorang ulama yang pernah belajar di Aceh. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pusat pencerahan ilmu pengetahuan di Indonesia di mulai dari Aceh.[28]
Kenyataan sejarah tersebut memang diakui oleh para peneliti sejarah. Namun sayangnya, sejarah tersebut tidak dapat diulangi oleh generasi selanjutnya. Setelah kedatangan Belanda dan diteruskan oleh pergolakan demi pergolakan di Aceh telah menyebabkan pencarian ilmu pengetahuan di Aceh mengalami kemunduran pada titik nol. Hal ini memang sangat berlebihan, tapi jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, kontribusi generasi Aceh terhadap peningkatan ilmu pengetahuan di Aceh sangat lamban. Hal ini disebabkan oleh gejolak di Aceh semenjak pasca kemerdekaan sampai dengan sekarang ini.
3. Agama
Di Aceh, agama (baca: Islam) menjadi sendi pokok dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua lapisan masyarakat selalu melandaskan pada agama Islam. Sehingga, kekuataan agama menjadi salah satu pendorong dalam perjuangan bangsa Aceh. Melalui agama, kerajaan juga bisa berkembang. Lewat agama juga, ilmu pengetahuan bisa mencapai kemajuan yang sangat berarti. Demikian, juga agama menjadi hukum bagi masyarakat Aceh.
Sebagai contoh, dua aspek di atas yaitu politik dan ilmu pengetahuan selalu mengedepankan Islam sebagai landasannya. Undang-undang Kerajaan Aceh hampir semuanya berdasarkan pada agama.[29] Untuk mengambarkan data sejarah yang nyata tentang peran agama di Aceh, dalam manuskrip kitab Tazkirah Thâbaqat Jumû‘ Sultân As-Salâtîn disebutkan bahwa:
“Syahdan ( ) maka ketahui oleh hai talib bahwa pada negeri Islam dalam seluruh dunia ini dari dahulu sampai sekarang hingga akan datang tiap-tiap kerajaan ( ) Islam hendaklah memegang tiga perkara pertama qanun syara‘ Allah kedua qanun syara‘ Rasul Allah ketiga qanun syara‘ kerajaan maka tiga macam ( ) seperti yang tersebut maka hendaklah memegang oleh sulthan-sulthan dengan teguh supaya negeri aman dan rakyat senang hidup dengan makmur ( ) wajib itu dua macam yang pertama wajib fardhu ain yang kedua wajib fardhu kifayah”.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa agama merupakan tiang pokok masyarakat Aceh. Karena itu, dengan semangat agama, semua persoalan di Aceh dapat diselesaikan. Dalam melawan penjajah, rakyat Aceh selalu melibatkan “agama di depan”. Tujuan yang hendak dicapai oleh agama adalah syahid.[30] Dan jika sudah syahid maka syurga adalah impian terakhir. Akibatnya, para syuhada di Aceh sangat banyak sekali. Ringkasnya, dengan ideologi jihad, kedatangan penjajah Belanda, menurut Azyumardi Azra, menjadi semacam “ rahmat terselubung”, bagi kelompok-kelompok etnis Muslim di kawasan ini.[31]
Pada saat yang sama, persoalan di Aceh juga selalu melibatkan agama. Misalnya, Gerakan Di/TII yang dipelopori oleh Daud Beureueh dalam Manifesto Pemberontak Aceh juga mengatasnamakan agama sebagai alasan gerakan tersebut. Untuk lebih lengkapnya mengenai teks manifesto tersebut, kami sebutkan di bawah ini:
“Atas nama Allah kami rakyat Aceh sudah membuat sejarah baru di atas persada tanah tumpah darah, kami berkehendak membentuk suatu Negara Islam.
Kami telah jemu melihat perkembangan-perkembangan atas dasar Negara Republik Indonesia, betapa tidak, sejak dahulu kami berharap, bercita-bercita negara berkisar atas dasar Islam, akan tetapi jangankan terujud apa yang kami idam-idamkan, malahan sebaliknya semakin hari tampak pada kami ada di antara pemuka-pemuka Indonesia mencoba membelok ke arah yang sesat.
… Jika pidana Tuhan tidak berlaku, itu berarti menyimpang dari Ketuhanan Yang Maha Esa.
Andaikan Undang-Undang Dasar R.I. sudah memberi jaminan kemerdekaan beragama c.q. Islam, sudah lama pula dapat berjalan hukum-hukum agama di tanah Aceh, yang rakyatnya 100 persen beragama Islam.
Malahan oleh Kejaksaan Agung sendiri pernah mencoba-coba mengeluarkan berkhotbah di mesjid atau di tempat-tempat lain yang katanya tempat agama, yang berisi politik, padahal bagi kami politik ialah sebagian dari agama yang kami anut, kalau boleh kami mengatakan bahwa Kejaksaan Agung ialah instansi resmi yang mula-mula mencoba menghalangi-halangi kami beragama, yang harus diminta pertanggung jawaban di hadapan Undang-Undang Dasar Negara dan di depan Tuhan, jika orang dari Kejaksaan Agung juga beragama Islam dan beriman kepada Tuhan.
…. Rasa sedih dan kesal ini memupuk keinginan kami untuk membentuk suatu Negara Islam. Andaikata orang menyalahkan kami, maka kesalahan itu harus mula-mulanya ditimpakan kepada pundak Sukarno sendiri.
Andaikata orang mengatakan pembentukan Negara Islam di Aceh berlawanan dengan hukum dan mengakibatkan kekacauan, kami akan mengatakan bahwa tindakan kami ini disebabkan oleh hukum yang kacau atau karena kekacauan hukum; tentu tidak heran; kekacauan akibat (karena) kekacauan hukum, tentu orang tidak dapat memperbaiki akibat sebelum ia sendiri memperbaiki asal pokok musababnya….”[32]
Jadi, di Aceh agama dijadikan standar dalam segala sisi kehidupannya. Jika sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan agama, maka hal tersebut tidak akan dipermasalahkan. Begitu juga sebaliknya, jika ada masalah bertentangan dengan agama, maka nyawa sebagai taruhannya. Untuk itu, sejarah telah membuktikannya.
Pantulan Sejarah Terhadap Persoalan Aceh Sekarang
Dari uraian sejarah di atas, tampaknya gejolak di Aceh tidak lepas dari konteks sejarah. Karenanya, untuk menganalisa masalah Aceh, berikut ini akan diketengahkah beberapa titik balik sejarah Aceh yang sedikit banyak mengalami paradoks.
a) Setelah melihat kekuatan politik Aceh tempoe doeloe, maka hal yang pertama yang terjadi di Aceh adalah merosotnya kekuataan politik di Aceh, baik itu di kalangan rakyat baik di dalam maupun di luar Aceh. Dahulu, persatuan kerajaan Islam Aceh telah menyebabkan daerah ini mampu menguasai sampai ke Semenanjung Malaka. Sekarang setelah tidak adanya persatuan politik tentang kesadaran akan sebagai rakyat Aceh, persoalan yang terjadi tidak pernah terselesaikan. Indikasi yang menunjukkan ke arah tersebut nyata di depan mata. Dulu, rakyat Aceh mendapat bantuan dari berbagai kerajaan (negara) Islam. Sekarang setelah kekuatan politik lemah, tidak ada satu negara pun yang membantu Aceh.
Selain indikasi di atas, rakyat Aceh tidak pernah bersatu dalam satu ikatan. Dalam konteks ini, istilah lain adalah pengkhianat. Hampir seluruh perjuangan bangsa Aceh kandas di tangan pengkhianat. Para syuhada, kecuali gugur secara wajar, banyak juga yang wafat karena ulah pengkhianat. Watak ini sampai sekarang masih membekas. Para pengkhianat ini selalu melintasi sejarah Aceh.[33] Mereka terkadang secara terang-terangan menjual Aceh kepada penjajah atau juga dengan cara diam-diam. Adanya pengkhianat ini telah mengkandaskan perjuangan bangsa Aceh sejak zaman Belanda. Sejauh pengetahuan penulis, Teuku Chik Di Tiro meninggal setelah diracuni oleh seorang janda. Cut Nyak Dhien ditawan oleh Belanda karena diberitahu oleh salah seorang kawannya. Masih banyak bentuk pengkhianatan lain yang sampai sekarang membekas dalam benak rakyat Aceh.
Selain pengkhianatan, di Aceh juga terjadi “dendam sejarah” yang sampai sekarang masih api dalam sekam. Akibat dari “dendam sejarah”, tidak heran jika ada segolongan rakyat Aceh tidak punya keinginan menyelesaikan kasus Aceh. “Dendam sejarah” tersebut adalah “Peristiwa Cumbok”. Peristiwa ini, menurut Taufik Abdullah, “revolusi sosial” di Aceh. Inti dari “revolusi” tersebut banyak uleebalang yang menemui ajalnya, dan banyak pula harta mereka yang dirampas.[34] Efek dari peristiwa tersebut telah menyebabkan rasa persatuan di kalangan rakyat Aceh melentur sehingga sangat mudah dimasuki oleh “penjajah” model baru. “Penjajah” ini sangat paham akan kekuatan rakyat Aceh, sehingga yang pertama kali dikikis habis adalah rasa “memiliki” Aceh.
Orang Aceh Utara mengatakan bahwa dirinya adalah orang “paling” Aceh, sebab kawasan ini banyak industri vital. Begitu juga Aceh Pidie juga menyebutkan bahwa dirinya orang “paling” Aceh, karena dari daerahnya banyak muncul tokoh-tokoh penting dalam sejarah Aceh. Pada saat yang sama, orang Gayo yang tidak ingin disebut orang Aceh. Karenanya, mereka selalu menyebut dirinya “orang Gayo”.[35] Padahal dalam sejarah bangsa Aceh, persaingan tingkat inter-etnis lokal tidak pernah ada. Dahulu para pahlawan dalam bergerilya hampir menyisir seluruh bagian Aceh. Kenapa sekarang, ketika sudah merdeka kita membuat “kapling ideologi”. Sesungguhnya, hal tersebut tidak pernah terjadi dalam sejarah Aceh.
Kenyataan ini, adalah potensi yang menciptakan perpecahan di Aceh. Potensi tersebut dapat dibaca oleh “musuh” baik itu dari dalam maupun dari luar. Karenanya tidak heran jika sekarang peta pergerakan perjuangan di Aceh sangat beragam. Di tingkat lapangan ditemui GAM dengan rakyat. Di tingkat menengah dijumpai para mahasiswa dan aktivis LSM yang mempunyai beragam orientasi tentang persoalan Aceh. Di tingkat atas, para elit politik yang “bermain” di Jakarta, Aceh dan luar negeri.
GAM cenderung mendekati rakyat dengan pendekatan sejarah. Belum lagi persoalan GAM Cantoi[36] yang memeras rakyat. Di sini membuktikan rakyat Aceh belum matang dalam mempelajari politik. Memang jika semua kita membenarkan gerakan kita atas nama sejarah, maka sejarah yang mana yang kita harapkan dari masyarakat. Mengapa sejarah tersebut tidak dijadikan sebagai pusat kesadaran kolektif masyarakat. Maksudnya, jika menurut sejarah, bangsa Aceh berhasil mengapa keberhasilan tersebut tidak kita contoh. Apakah sejarah hanya untuk membangkitkan semangat tanpa program dan target yang nyata.
Hal yang sama juga terjadi pada para mahasiswa penggagas Referendum, yang menurut hemat penulis telah tidak bertanggung jawab dalam menggulirkan isu tersebut. Awalnya, isu tersebut bisa menjadi pendidikan politik masyarakat Aceh. Sayangnya istilah tersebut diartikan dengan merdeka. Kekeliruan ini tentunya dimanfaatkan oleh kalangan yang menginginkan Aceh tetap kacau. Secara istilah, referendum adalah penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka menentukan (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat). Dalam hal ini, referendum ada dua yaitu referendum fakultatif tidak wajib meminta pendapat secara langsung (bergantung pada putusan penguasa), misal penetapan undang-undang; referendum obligator kewajiban meminta pendapat rakyat secara langsung dalam mengubah sesuatu, misal perubahan konstitusional.[37] Dalam konteks tersebut, nampaknya sosialisasi referendum di Aceh telah mengalami kegagalan sehingga yang ditengarai oleh Jeda Kemanusiaan yang secara hukum tidak mengakhiri proses pembantaian di Aceh. Sekali lagi, kalangan yang mensosialisasikan referendum telah terjebak ke dalam makna “merdeka” sehingga rakyat mengharapkan referendum yang oleh mahasiswa sampai saat ini belum bisa direalisasikan. Namun demikian, usaha ke arah tersebut patut dihargai meskipun dengan beberapa catatan di atas.
Adapun para elit politik dapat dibagi ke dalam empat golongan.
Pertama, mendukung sepenuhnya dan secara lantang mensuarakan kehendak rakyat Aceh. Namun terkadang usaha mereka kandas di tengah jalan. Ada yang diculik, dibunuh dan dibantai. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah Aceh tidak pernah terselesaikan.
Kedua, mendukung tapi tidak memperlihatkan dukungannya. Biasanya dukungan tersebut muncul ketika menyimak berita tentang Aceh. Kelompok ini biasanya sangat dekat dengan orang Aceh, tapi tidak punya “kuasa” dalam pengambilan keputusan politik.
Ketiga, tidak mendukung sepenuhnya. Kalangan ini secara terang-terangan memperlihatkan ketidaksukaan pada rakyat Aceh. Mereka ada yang terdiri dari orang Aceh dan bukan orang Aceh. Orang Aceh yang dimaksud adalah mereka yang punya “dendam sejarah” dan telah menikmati hasil keringatnya yang tidak mau “diganggu”. Sedangkan orang luar Aceh merupakan orang-orang yang punya kepentingan di Aceh baik secara politik maupun ekonomi. Nampaknya faktor terakhir lebih dominan ketimbang faktor pertama.
Keempat, tidak mendukung penyelesaian kasus Aceh, namun tidak memperlihatkan ketidakinginannya. Mereka cenderung bermain di belakang layar. Tujuan yang hendak dicapai, adalah sama dengan kelompok ketiga, tapi mereka punya pilihan lain jika keinginan mereka tidak tercapai. Atau dengan kata lain, jika perjuangan rakyat Aceh berhasil, maka mereka akan ke pilihan lain.
b) Pendidikan Aceh telah merosot ke titik nadir. Dulu Aceh menjadi pusat studi di Asia Tenggara. Sekarang, malah sebaliknya, kita orang Aceh “hengkang” dari Aceh ke luar Aceh dan mutu pendidikannya sangat rendah. Di tambah lagi mutu SDM kita sangat rendah. Akibatnya, dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang tinggi tidak didukung oleh SDM yang memadai yang akhirnya hasil-hasil bumi Aceh banyak dinikmati oleh non-bangsa Aceh.
Hemat penulis, kekuatan pendidikan di Aceh, sekarang ini banyak dikikis habis. Bukti konkret adalah pembakaran sekolah-sekolah dan sibuknya mahasiswa Aceh dalam gejolak di Aceh. Sehingga dapat dibayangkan, satu generasi Aceh akan bodoh total. Ramalan ini bukan mengada-ada. Jika usia 7 tahun (2000) tidak sekolah atau tidak ada keamanan, maka umur 25 tahun (2018) sebagai usia produktif akan berkurang mutu pendidikan di Aceh. Bisa dibayangkan bagaimana sejarah masa depan Aceh nantinya. Semua aspek kehidupan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan rakyat. Andai sejarah masa depan menjadikan bangsa Aceh merdeka, satu pertanyaan yang mungkin muncul yaitu bagaimana mutu pendidikan bangsa Aceh. Kita tentunya tidak ingin seperti Timor Timur. Begitu juga jika diberlakukan otonomi khusus, apakah bangsa Aceh siap mengelola hasil-hasil buminya.
Keraguan ini bukan tanpa alasan mengingat seluruh lapisan masyarakat Aceh telah melupakan pendidikan. Hampir semua bangsa Aceh melupakan faktor pendidikan, khususnya bagi generasi muda. Begitu juga, jika semua pemuda Aceh memanggul senjata atau demontrasi maka dapat dibayangkan pada tahun 2015, posisi Aceh dalam percaturan ilmu pengetahuan akan mundur ke belakang. Untuk itu, perlu dikembangkan lagi wajib belajar bagi mereka dan mau kembali membangun Aceh.
Kenyataan bahwa di Aceh terjadi pembodohan besar-besaran adalah bukan hal yang mesti dipungkiri. Sebab, cara pembodohan tersebut di Aceh sangat sistematis dan ini harus disadari oleh kita. Cara-cara tersebut adalah dengan membakar sekolah-sekolah, membantai para ulama,[38] dan membuat ketegangan di tengah-tengah masyarakat Aceh. Menurut sejarah, hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh Belanda ketika menjajah Aceh. Misalnya, dayah dibakar berikut kitab-kitabnya, ulama dibantai, masyarakat dibuat resah. Dengan demikian, dibutuhkan kesiagaan penuh untuk membangkitkan kembali pendidikan di Aceh.
Jika hal di atas, tidak menjadi perhatian kita, maka perjuangan bangsa Aceh akan sia-sia. Sebab, di era globalisasi yang akan berperan adalah teknologi dan ekonomi, di samping juga agama akan memegang peran yang signifikan.[39] Artinya, apabila bangsa Aceh ingin membuat sejarah lagi, maka tiga hal tersebut harus menjadi titik tekan dalam segala bentuk perjuangannya.
c) Agama tidak lagi menjadi perhatian dalam kehidupan di Aceh. Fenomena ini tidak sepenuhnya benar, namun arah kesana sudah nampak. Agama tidak lagi menjadi pertimbangan di Aceh. Nyawa, harta, wanita adalah hal yang biasa. Seorang yang membenci orang lain, nyawa adalah taruhannya. Hal ini memang telah terjadi sejak zaman penjajahan di Aceh. Dari waktu ke waktu, setiap nyawa pasti melayang di bumi ini. Bagi yang berjuang, nyawa adalah taruhan yang sangat cocok untuk mencapai kesyahidan. Dalam ini, agama adalah landasan. Tapi, bagi para “penjajah” nyawa adalah salah satu dari bentuk ”komando” yang harus dipatuhi.
Memang di Aceh akan berlakukan otonomi khusus yang diterjemahkan dengan semua urusan kecuali tiga urusan, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan (keluar) dan moneter, diserahkan kepada Daerah (selanjutnya disebut Nanggrau Aceh Darussalam – NAD). Atau dalam bahasa Dzulkarnain Amin, Aceh memperoleh “kemerdekaan ke dalam”.[40]
Dengan demikian, peran agama akan sangat menentukan tentang bagaimana aplikasi dari otonomi khusus. Untuk itu, ulama, umara dan rakyat Aceh sejatinya menjadikan agama sebagai landasan dalam pelaksanaan otonomi tersebut. Namun kendala muncul lagi yaitu bagaimana menerapkan agama dalam masyarakat yang sudah terkena “sindrom militerisme”. Istilah ini sengaja kami angkat guna memperlihatkan bahwa di Aceh sekarang gejala militerisme banyak ditemukan. Maraknya penghilangan nyawa secara paksa dan penyebaran fitnah adalah salah satu fenomena yang banyak ditemui di Aceh. Akhirnya, posisi agama akan sangat dilematis yang pada gilirannya penerapan agama ( baca: hukum) di Aceh akan menemui jalan buntu. Sebab, untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan undang-undang yang konon berita yang diterima RUU No.44 tahun 1999 belum disahkan sampai tulisan ini disampaikan.[41]
Jika RUU tersebut disahkan, maka perjuangan bangsa Aceh akan berhasil, namun jika tidak, perjuangan bangsa Aceh akan menebarkan sebanyak mungkin kehilangan nyawa dan fitnah. Dengan perkataan lain, “jalan buntu” di atas harus dicari “jalan alternatif” yaitu kemauan politik (political will) dari lima komponen perjuangan bangsa Aceh di atas (GAM, rakyat, mahasiswa, LSM, dan elit politik Aceh). Kelima komponen tersebut, sejatinya duduk dalam “satu meja” bermusyawarah bukan malah menciptakan konflik yang sama sekali merugikan masing-masing pihak.
Manakala hal tersebut terjadi, memori sejarah perjuangan bangsa Aceh tentang keserasian antara ulama, umara dan rakyat di Aceh akan terulang kembali. Kita mungkin masih ingat ketika perjuangan bangsa Aceh melawan Belanda dimana cara Belanda dalam menaklukan Aceh adalah dengan cara memecah belah bangsa Aceh, gambaran ini dapat diringkas sebagai berikut:
“Dalam usaha mereka untuk menguasai Aceh, Belanda mencoba untuk memisahkan kekuatan-kekuatan tradisional –sultan, uleebalang, dan ulama- dengan menawarkan “pemerintahan sendiri” (“self governing”) bagi para uleebalang dengan cara korteverklaring (deklarasi singkat) pada tahun 1874. Cara ini menghasilkan hubungan yang tidak harmonis antara uleebalang dan ulama, yang akhirnya terjadi konflik berdarah di antara mereka selang beberapa waktu setelah Indonesia merdeka pada 1945. Pada dasarnya, perselisihan ini merupakan hasil rekayasa Belanda yang dianjurkan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad ini.”[42]
Akhirnya,
“Dengan cara-cara di atas, Belanda berhasil memecah belah persatuan rakyat Aceh, yang pada gilirannya menyebabkan adanya konflik yang berkelanjutan antara kelompok yang pro-sultan dan pro-uleebalang. Di antara para uleebalang, ada yang sudah mempersiapkan untuk merebut korteverklaring, dan ada juga beberapa yang masih setia pada sultan. Kendatipun demikian, sultan memperoleh dukungan yang sangat kuat dari ulama, hal mana sangat anti terhadap Belanda. Dengan begitu, mereka memimpin perlawanan terhadap mereka. Bersama dengan para aristokrat yang masih mendukung sultan, para ulama ikut perang yang dilandaskan pada ajaran agama. Dengan menggunakan strategi perang gerilya, mereka terus-menerus berjuang dalam beberapa tahun untuk menghalangi Belanda yang membawa agama dalam kontrol mereka selama sepuluh tahun setelah sultan ditawan. Dengan demikian, Belanda tidak berhasil memerintah di Aceh sampai akhir tahun 1918, selama 45 tahun setelah meletus berperang.”[43]
Demikianlah yang dilakukan oleh Belanda dan nampaknya apa yang terjadi sekarang di Aceh tidak jauh berbeda dengan ilustrasi di atas. Teori Snouck dipraktekkan secara sistematis namun agak sedikit kejam, khususnya dalam bidang agama. Bukan maksud untuk membangkitkan rasa kemarahan, tragedi penerapan DOM di Aceh adalah bukti sejarah hitam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini, korban nyawa, harta, “perawan” (baca: pemerkosaan) adalah catatan pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum ada satu pun disidangkan menurut hukum negara Indonesia atau hukum Islam.
Setidaknya, menurut laporan catatan berbagai sumber, catatan pelanggaran HAM di Aceh sebagai berikut: Versi FP HAM 25 Kasus Tersadis. 1) Tak boleh tutup aurat saat shalat; 2) digorok dan rumah korban dibakar; 3) rumah terbakar, tak diganti rugi; 4) diikat, ditarik ramai-ramai, lalu didor; 5) diganduli batu, lalu dibenam ke sungai; 6) ajimat dicabut dan disiksa; 7) ditembak, kemudian kuburnya dibongkar; 8) digebuk, dicampak ke mobil, lalu dikubur massal; 9) ditembak di depan umum; 10) diciduk di masjid, dibantai di lapangan; 11) dijadikan tameng saat bertempur lawan GPK; 12) tangan dibedah, ditetesi air asam; 13) disiksa hingga mata kiri tak berfungsi; 14) diculik serempak lalu dibunuh massal; 15) santri diculik, lalu dibantai; 16) kepala dikuliti depan anak; 17) ditembak dalam sumur; 18) ditaruh pemberat besi; 19) disiksa sembilan malam, dilapari; 20) suami dibuang, istri disentrum: 21) semua gigi dirontokkan; 22) cacat karena dipukul dengan balok; 23) tulang rusuk dipatahkan; 24) digantung, kepala ke bawah; 25) diperkosa, hamil, ditinggal.[44]
Menurut versi AGAM, ada dua belas cara penganiayaan yang terjadi di Aceh terhadap tahanan selama DOM sebagai berikut: 1) disepak dan diterjang di bagian yang lemah dengan tujuan mencederakan; 2) pelir tahanan dijepit hancur dengan menggunakan tang; 3) Kaki kursi diletakkan ke atas anak jari kaki tahanan itu, kemudian para tentara duduk di atasnya untuk menambahkan tekanan atas anak kaki mereka sampai remuk–redam hancur berdarah; 4) telapak tangan dan kaki tahanan dipaku seperti orang yang disalin, hanya tiang salibnya saja yang tidak digunakan; 5) tahanan-tahanan direbus dengan air panas; 6) tahanan direndamkan berhari-hari atau berminggu-minggu dalam kolam air najis; 7) tahanan digantung kepala ke bawah dan kaki ke atas; 8) tubuh tahanan ditonjok dengan puntung rokok dan besi panas; 9) tahanan dipukuli dengan batang besi atau tangkai-tangkai yang keras berlapiskan papan tipis (triplek) di antara senjata tajam dengan tubuhnya supaya bila dipukuli tinggal bekas tetapi rusak di dalam badan tersebut semakin parah, sehingga mereka muntah darah; 10) kawat besi yang tajam dimasukkan ke dalam saluran kencing kemaluan kemudian diputar-putar kawat itu sehingga mengakibatkan sakit yang tidak terhingga; 11) tahanan-tahanan diikat ke sebuah balok es 1,5 meter, yang berjam-jam lamanya baru cair. Begitu mencair es batu tersebut, tahanan tersebut menjadi dan sudah tidak sadarkan diri; 12) ada di antaranya yang dicungkil matanya.[45]
Adapun pelanggaran HAM terhadap perempuan adalah menarik untuk mengutip versi Al-Chaidar (Aceh Bersimbah Darah), dkk. ada 12 cara yaitu 1) wanita Aceh diperkosa tiga tentara; 2) pelecehan seksual terhadap kaum wanita; 3) diperkosa, hamil, lalu ditinggal begitu saja; 4) gadis korban perkosaan melahirkan anak pemerkosa; 5) diperkosa sambil berdiri; 6) diperkosa, disetrum dan dicambuk dengan kabel; 7) ditelanjangi massal; 8) gadis cacat diperkosa oleh tentara yang sedang mabuk; 9)suami diculik, istri dilecehkan; 10) diambil paksa dan diperkosa; 11) diarak telanjang, lalu didor; 12) digagahi di depan anaknya.[46]
Data-data di atas adalah bukti nyata bahwa agama tidak lagi disegani oleh para pelanggar HAM. Ini membuktikan bahwa sebutan Serambi Mekkah tidak tepat lagi. Sebab jika yang namanya Mekkah, maka setiap darah di atas tempat tersebut adalah haram hukumnya kecuali murtad. Karena itu, sebutan “Serambi Mekkah” harus didefinisikan kembali dalam konteks ke-Aceh-an baru.
Paparan di atas merupakan pengingkaran sejarah bangsa Aceh terhadap apa yang sudah dibangun oleh para pendahulu ternyata disia-siakan. Dalam hal ini, ada pendapat yang menyebutkan mereka (para indatu kita) telah berjuang dan berkarya dengan baik sesuai dengan masanya. Kita tidak boleh bertepuk tangan atas kejayaan mereka, kita justru dituntut untuk berkarya sendiri.[47] Oleh karenanya tuntutan tersebut harus menjadi agenda kita semua sebagai generasi baru Aceh.
Dari paparan di atas ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Pertama, bahwa perjuangan bangsa Aceh merupakan tugas kita semua rakyat Aceh, tanpa kecuali. Oleh karena itu, skat-skat perbedaan antara kita seharusnya mulai di kikis. Dengan cara demikian, kajian sejarah di atas, merupakan salah satu pedoman dalam melakukan perjuangan.
Kedua, bentuk perjuangan dengan kesadaran sejarah adalah perjuangan yang menyeluruh. Maksudnya, perjuangan bangsa Aceh harus dilaksanakan secara kolektif tanpa ada pengembosan atau pengkhianat. Jika sejarah, membuktikan bahwa bangsa Aceh mampu mengusir penjajah, mengapa kita di era modern tidak mampu berbuat demikian. Dengan perkataan lain, perjuangan bangsa Aceh harus didefinisikan ulang yaitu perjuangan bangsa Aceh untuk golongan, kalangan atau demi tanah Rencong. Jika demi kalangan dan golongan, maka sampai kapanpun perjuangan bangsa Aceh akan tetap mengalami kegagalan. Namun jika perjuangan demi tanah pertiwi Aceh, maka Insya Allah bantuan akan datang seperti para indatu kita dulu berjuang.
Ketiga, khusus bagi generasi muda adalah bagaimana mempersiapkan Aceh di masa depan bukan malah terjebak pada permasalahan politik yang tidak jelas. Oleh karenanya, pendidikan merupakan salah satu persiapan untuk arah ke sana. Sebab untuk mengharapkan generasi sekarang berjuang demi Aceh adalah harapan yang berlebihan. Karena, perjuangan selalu membutuh waktu dan ruang. Mereka tentu telah berjasa dan pada saat yang sama Aceh juga masih menunggu jasa-jasa kita.
Akhirnya, saran saya kepada kita adalah mari kita membuat sejarah yang akan dibaca oleh cucu kita sebagaimana kita membaca sejarah nenek moyang kita. Sebab walau bagaimanapun sejarah adalah cermin suatu bangsa.
[1]H.M. Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961).
[2]Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah, (Jakarta: Sinar Harapan, 1987); idem, Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 1999).
[3]Lee Kam Hing, The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760-1824, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995).
[4]C. Snouck Hurgronje, Aceh: Rakyat dan adat Istiadatnya, 2 Jilid (Jakarta: INIS, 1997).
[5]Sejauh ini, meskipun bukan peneliti sejarah, penulis telah mengumpulkan beberapa literatur sejarah tentang Aceh yang ditulis oleh berbagai pihak. Untuk lebih mendalami dan mengerti sejarah Aceh, maka penulis menganjurkan untuk membaca beberapa karya berikut: Luthfi Auni, ”The Decline of The Islamic Empire of Aceh,” Tesis M.A. McGill University, (1993); Amirul Hadi, ”Aceh and The Portuguese: A Study of the Struggle of Islam in Southeast Asia 1500-1579,” Tesis M.A. McGill University, (1992); M. Hasbi Amiruddin, ”The Response of The Ulama Dayah to the Modernization of Islamic Law in Aceh,” Tesis M.A. McGill University, (1994); Hamdiah Latif, ”Persatuan Ulama Aceh (PUSA): Its Contribution to Educational Reforms in Aceh,” Tesis M.A, McGill University, (1992); Amran Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990). Namun dewasa ini, sejak pergolakan Aceh, sejarah Aceh juga masih ditulis. Baca misalnya, Al-Chaidar, dkk., Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) Di Aceh 1989-1998, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1999); Yusra Habib Abdul Ghani, Mengapa Sumatera Menggugat, (Biro Penerangan Acheh-Sumatera National Liberation Front, 2000); Fikar W. Eda dan S. Satya Dharma (peny.), Aceh Menggugat: Sepuluh Tahun Rakyat Aceh di Bawah Tekanan Militer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999); Kaoy Syah dan Lukman Hakiem, Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah: Proses Pembentukan UU No.44/1999, (Jakarta: Pengurus Besar Al-Jami’iyatul Washliyah, 2000).
[6]Kasus kongkret adalah apa yang dialami oleh bangsa Indonesia, menurut Asvi Warman Adam, pada masa awal Orde Baru, strategi pengendalian sejarah mencakup dua hal: pertama, mereduksi peran Soekarno, dan kedua, membesar-besarkan jasa Soeharto. Lihat Asvi Warman Adam, ”Pengendalian Sejarah Sejak Orde Baru,” dalam Henri Chambert-loir dan Hasan Muarif Ambary (ed.), Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 572.
[7]Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1996), 161.
[8]Asvi Warman Adam, Pengendalian Sejarah, 576.
[9]Sejauh pengetahuan penulis, pendekatan sejarah sering digunakan oleh Gerakan Acheh Merdeka dalam mensosialisasikan program-programnya. Lihat misalnya Tengku Hasan di Tiro,”Perkara & Alasan Perdjuangan Angkatan Atjèh Sumatera Merdéka”, Tjeramah :Dimuka Scandinavian Association of Southeast Asian Social Studies Göteborg, Sweden, 23 Agustus, 1985. Untuk membuktikan asumsi ini, penulis mengutip sepenggal ceramah Hasan Di Tiro,” Lama sekali sebelum kedatangan pendjadjahan2 Eropa Barat ke Dunia Melaju (Asia Tenggara) Atjeh sudah mendjadi satu negara merdeka jang berdaulat jang diakui dunia internasional di Sumatera. Pada waktu itu negara merdeka itu lebih terkenal dengan nama Keradjaan Atjeh, tetapi kemudian mendjadi lebih terkenal dengan nama sebuah pelabuhannja jang sering dikundjungi oleh kapal-kapal Eropa, jaitu pelabuhan ‘Samudra’ di Atjeh Utara, jang dari padanja berasal nama Sumatera. Buku Larouse Grand Dictionnaire Universelle, menggambarkan Keradjaan Atjeh pada waktu itu sebagai "bangsa jang paling berkuasa di Dunia Melaju atau Hindia Timur, pada achir abad ke-16 dan sampai pertengahan abad ke-17. ("Vers la fin du XVIe siècle et jusqu’ à la moitië du XVIIe, les Achins etaient la nation dominante de l’archipel Indien.") Vol.I, p.70, Paris, 1886. Sebuah sumber sedjarah jang besar jang lain, La Grand Encyclopedie, menulis sebagai berikut: "Pada tahun 1582, bansa Atjeh sudah meluaskan kekuasaannja atas pulau2 Sunda (Sumatera, Djawa, Borneo, dll), atas satu bagian dari semenandjung Tanah Melaju, dan mempunjai hubungan dengan segala bangsa jang melajari lautan Hindia, dari Djepang sampai ke Arab. Sedjarah peperangan jang lama sekali jang dilantjarkan oleh bangsa Atjeh terhadap bangsa Portugis jang menduduki Malaka sedjak permulaan abad ke-16, adalah halaman2 jang tidak kurang kemegahan dan kebesarannya dalam sedjarah bangsa Atjeh. Pada tahun 1586, seorang Sultan Atjeh menjerang Portugis di Malaka dengan sebuah armada yang tediri dari 500 buah kapal perang dan 60,000 tentera laut." ("En 1582, ils avaint étandu leur Malacca depuis le commentcement du XVIe siècle n’est pas une des pages les moins prépondérance sur les iles de la Sonde, sur une partie de la Presque ‘ile de Malacca, ils étaient en relation avec tous les pays que baigne l’océan Indien depuis le Japan jusqu´ à glorieuse de l’ histoire des Atchinois. En 1586, un de leur Sultans attaque les Portugais avec une flotte d’ environ 500 voiles montée par 60,000 marins." (Vol.IV,p.402, Paris,1874)”. Lihat juga “Pernjataan Atjeh Sumatera Merdeka Kembali,” oleh Tengku Hasan di Tiro, 4 Desember, 1976, dimuat dalam AGAM: Madjallah Angkatan Atjeh Meurdehka, No.40 (1991), 72-74; idem,”Nasionalisme Indonesia,” Suara Acheh Merdeka, edisi VI Desember (1995), 22-23. Tulisan ini kembali dimuat dalam Yusra Habib Abdul Ghani, Mengapa Sumatera Menggugat, 42-52. Lebih dari itu, Tengku Hasan Di Tiro, konon menurut kabar tersiar adalah Wali Negara Acheh Merdeka. Dia memilih dirinya sendiri sebagai wali negara. Berikut petikan salah satu tulisan Hasan Di Tiro, ”Saya telah menanda-tangani Surat Pernyataan Acheh/Sumatera Merdeka sebagai Negara Sambungan atas kelegalan Hak Successor State sebab pada waktu ini saya yang berhak (bertugas) sebagai Wali Negara Acheh sebagai Tengku Tjhik di Tiro menggantikan (cetak miring dari penulis) Yang Mulia Nenekanda Tengku Tjhik Mahyeddin dan Pamanda Tengku Tjhik Ma’at, yang gugur pada 3 Desember, 1991, dalam perang dengan Belanda.” Lihat Tengku Hasan Di Tiro,”Konsep-Konsep Ideologi Acheh Merdeka,” Suara Acheh Merdeka, (1995), 34. Untuk mengetahui latarbelakang mengapa Hasan di Tiro mendirikan organisasi Acheh Merdeka, baca Tengku Hasan di Tiro, The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro, (National Liberation Front of Acheh Sumatra, 1984).
[10]Penting dicatat bahwa pada saat kekuatan-kekuatan imperialis Barat telah mematahkan kekuatan sebagian besar negara-negara Islam, pada saat itulah, pada permulaan abad XVI, lahirlah “Lima Besar Islam” yang terikat dalam suatu kerjasama ekonomi, politik, militer dan kebudayaan. Lima Besar Islam yang dimaksud yaitu: 1. Kerajaan Turki Usmaniyah, yang berpusat di Istambul, 2. Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara, 3. Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, 4. Kerajaan Akra di India, 5. Kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara. Baca, Ali Hasjmy,”Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan,” dalam Ismail Suni (ed.), Bunga Rampai Tentang Aceh, 208.
[11]Asal kata Peureulak menurut Ali Hasjmy adalah sebagai berikut: di satu daerah di wilayah Aceh Timur sekarang, banyak sekali tumbuh kayu besar, yang bernama “Kayei Peureulak” (Kayu Perlak), bahkan telah merupakan “Rimba Peureulak”. Kayei tersebut sangat baik untuk bahan pembuatan perahu, kapal, sehingga banyak dibeli oleh perusahaan-perusahaan kapal/perahu.… Kemudian para pengembara/pedagang sebelum “Zaman Islam” yang datang dari Cina, Arab, Persia, Hindi, Italia, Portugis dan lain-lainnya melalui Selat Melaka dan singgah di Pelabuhan daerah Kayei Peureulak, terus menyebut pelabuhan yang mereka singgahi itu dengan “Bandar Perlak”. Lihat A. Hasjmy, ”Adakah Kerajaan Islam Perlak Negara Islam Pertama di Asia Tengara,” dalam A. Hasymy (ed.), Sejarah Masuk,
Artinya: Arab, China, Eropa, dan Hindia
Dari judul di atas, setidaknya ada tiga hal yang menjadi pertanyaan bagi kita yakni pertama, sejarah, perjuangan, dan bangsa Aceh. Tiga hal tersebut memang membutuhkan waktu yang lama untuk mengkaji atau mendiskusikannya. Sebab, sepengetahuan penulis, kajian tentang sejarah Aceh telah banyak ditulis baik itu oleh orang Aceh sendiri maupun orang luar. Misalnya, kajian H.M. Zainuddin,[1] Ibrahim Alfian,[2] Lee Kam Hing,[3] C. Snouck Hurgronje,[4] dan lain sebagainya.[5]
Karya-karya di atas, tentunya sudah pernah dibaca oleh kita semua. Karena itu, untuk menjelaskan sejarah perjuangan Aceh, nampaknya karya yang penulis kemukakan tersebut cukup membantu dalam memahami sejarah perjuangan bangsa Aceh. Apalagi, sekarang kondisi Aceh masih bergejolak. Karenanya, tujuan dari kajian kita pada bab ini adalah mencari titik-titik temu sejarah yang bisa dirakit kembali untuk perjuangan masyarakat Aceh. Dengan tujuan ini, diharapkan setiap rakyat Aceh punya kesadaran tentang sejarah yang tidak hanya untuk dijadikan bahan kebanggaan daerah, tapi juga bisa menciptakan sejarah yang pernah terjadi di tempoe doeloe. Dengan demikian, generasi yang sadar sejarah sangat diharapkan di era masa depan. Sebab, ketika sejarah tidak ditulis atau direduksi, maka sekian banyak kerugian yang diderita oleh suatu bangsa.[6]
Dalam konteks di atas, Taufik Abdullah menyatakan bahwa sejarah memang mempunyai arti ganda. Pertama, sejarah sebagai pengalaman empiris – sebagai sebagai peristiwa penting yang dilalui. Kedua, sejarah sebagai bagian dari kesadaran –ketika pengalaman itu telah diberi makna. Artinya, dari pengalaman empiris itu berbagai pesan dan pelajaran serta kebijaksanaan telah diambil.[7] Karena itu, Asvi Warman Adam berkesimpulan tentang fungsi sosial-politik dari sejarah tidak sama pada seluruh masyarakat di dunia. Ada yang berfungsi untuk mengkonsolidasikan persatuan dan kesatuan bangsa, ada pula yang bertujuan untuk menemukan jati diri suatu bangsa serta mencari “kebenaran” mengenai masa lampau, ada juga yang berperan untuk mencerdaskan warga negara.[8]
Dalam kerangka ini, kajian ini diajak untuk memahami sejarah perjuangan bangsa Aceh.[9] Sejarah sebagai konsolidasi yaitu dimana setiap kita menjadikan peristiwa masa lalu sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Aceh. Sejarah sebagai penemuan jati diri adalah sejarah yang menggambarkan bangsa Aceh sebagai salah satu bangsa yang pernah jaya di panggung dunia, yang pada gilirannya aspek ini membentuk jiwa yang mampu menatap ke depan bukan ke belakang sebagai romantisisme yang malah bukan menemukan jati diri akan tetapi lupa diri. Sejarah sebagai alat pencerdasan merupakan sejarah yang menjadikan setiap pembacanya mengerti dan belajar dari peristiwa tersebut bukan untuk mengulangi. Sebab, sejarah hanya berlaku untuk ruang dan waktu tertentu yang karenanya sejarah tidak untuk dikenang-kenang tapi bagaimana sejarah bisa memenangkan perjuangan.
Keberhasilan Bangsa Aceh Tempoe Doeloe
Mengungkapkan keberhasilan suatu bangsa –khususnya Aceh– dalam tinjauan sejarah bukan hal yang sulit. Sebab, Aceh merupakan salah satu kawasan di Nusantara yang beruntung yang sejarahnya banyak ditulis oleh para peneliti. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari karya-karya di atas yang menunjukkan bahwa sejarah Aceh masih dan akan terus ditulis. Namun, mengambil intisari mengapa perjuangan bangsa Aceh dahulu bisa berhasil bukan pekerjaan yang mudah. Sebab, jika sejarah ditulis oleh lawan, maka sejarah tersebut tidak akan terlepas dari bias penulis itu sendiri. Sebaliknya, sejarah yang ditulis oleh pribumi cenderung menonjolkan kelebihan tinimbang kekurangan. Untuk lebih jelasnya, maka pembahasan sub-bagian ini akan dibagi ke dalam tiga aspek yaitu, politik, ilmu pengetahuan, dan agama.
1. Politik
Dalam bagian politik, munculnya kerajaan Islam di Aceh merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh para generasi muda Aceh.[10] Secara kronologi, setidaknya ada lima kerajaan Islam di Aceh, yaitu Kerajaan Peureulak, Benua Tamiang, Kerajaan Islam Samudera Pasai, Kerajaan Islam Lamuri, dalam Kerajaan Islam Aceh.
Kerajaan Pereulak[11] merupakan kerajaan Islam pertama di Aceh, bahkan di Indonesia. H. M. Zainuddin mencatat bahwa Kerajaan Peureulak adalah lebih tua dari kerajaan Tumasik (Singapura) dan Bintan, juga jauh lebih tua dari kerajan Pasai dan Melaka, yang mungkin sebaya dengan kerajaan Aru dan Palembang (Sriwijaya), bahkan lebih tua dari kerajaan Majapahit di pulau Jawa.[12] Sistem ketatanegaraan, menurutnya, masih primitif atau rezim bangsa Melayu sekarang, yaitu kepala negerinya disebut Radjo/Radja, bawahannya disebut Kedjuren dan Penghulu, tidak seperti tradisi di Pasai, Pidie, dan Aceh Besar.[13]
Di samping kerajaan di atas, Kerajaan Benua Tamiang yang mula tidak beragama Islam,[14] kemudian setelah takluk ke Samudera dan memeluk agama Islam, maka oleh Sulthan Pasai diangkatlah raja lain yang bernama Radja Muda Sedia, pengganti Radja Dinok yang tewas dalam peperangan melawan tentera Samudra Pasai.[15]
Corak pemerintahan kerajaan ini disebutkan ber “Balai” dengan susunannya sebagai berikut: pertama, Raja dibantu oleh seorang Mangkubumi yang mempunyai tugas sehari-hari mengawasi jalannya pemerintahan dan ia bertanggung jawab kepada raja (pada waktu Raja Muda Sedia, mangkubuminya ialah: Muda Sedinu). Pertama, untuk mengawasi jalannya pelaksanaan hukum oleh pemerintah atau lembaga-lembaga penegak hukum yang dibentuk, diangkat pula seorang Qadhi Besar. Di Tingkat pemerintah daerah terdapat pula; a) Datuk-Datuk Besar yang memimpin daerah-daerah kedatuan; b) Datuk-Datuk Delapan Suku yang memimpin daerah-daerah suku perkauman; c) Raja-Raja Imam yang memimpin di daerah-daerah dan sekaligus juga bertindak sebagai sebagai penegak hukum di daerahnya.[16] Kerajaan ini pernah diserang pada sekitar tahun 1351 M., oleh kerajaan Majapahit.
Lebih lanjut, kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Islam Samudera Pasai. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-XI M. atau tepatnya pada tahun 1042 (433 H). Dan sebagai pendiri serta Sulthan yang pertama dari kerajaan ini adalah Maharaja Mahmud Syah, yang memerintah pada tahun 433-470, atau bertepatan dengan tahun 1042-1078 M.[17] Untuk mengambarkan tentang kerajaan ini, laporan Muhammad Ibrahim dan Rusdi Sufi nampaknya layak untuk disebutkan di sini:
Samudra Pasai adalah kerajaan yang bercorak Islam dan sebagai pemimpin tertinggi kerajaan berada di tangan Sulthan yang biasanya memerintah secara turun temurun. … di samping terdapat Sulthan sebagai pimpian kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti Menteri Besar (Perdana Menteri atau Orang Kaya Besar), Seorang Bendahara, seorang Komandan Militer atau Penglima Angkatan Laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris Kerajaan, seorang Kepala Mahkamah Agama yang dinamakan Qadi, dan beberapa orang Syahbandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para Syanbandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara Sulthan dan pedagang-pedagang asing.[18]
Sebagai bukti kemegahan kerajaan ini, kedatangan satu Musafir dari Timur Tengah dapat dijadikan sebagai data sejarah yang tidak dapat diabaikan, yakni Ibn Battutah. Ibnu Bathuthah datang ke Aceh pada 1345. Sedangkan yang menjadi tempat tujuan Ibn Bathuthah adalah Kerajaan Samudera Pasai. Ketika Ibn Bathuthah singgah di Pasai selama lima belas hari dalam tahun 746/1345, menyaksikan Islam aliran Sunni telah berkembang pesat dan madzhab yang dianut Syafi‘i. Kehidupan kerajaan bergaya Persia. Diceritakan pula bahwa di antara orang-orang besar kerajaan yang menjadi anggota majelis sultan termasuk Amir Daulah yang berasal dari Delhi, Qadli Amir Said dari Syiraz dan ahli hukum Tajuddin dari Isfahan. Ibn Bathuthah melaporkan juga bahwa banyak orang besar kerajaan pernah bertemu dengannya di Delhi.[19] Ibnu Di Bathuthah juga melaporkan perjalanannya mengatakan bahwa dalam sebuah pengertian politis, Samudera adalah pos luar yang paling akhir dari Dar al-Islam. Sekalipun kota-kota lainnya di sebelah Selatan sepanjang pantai Sumatra telah mengembangkan dengan suburnya permukiman-permukiman komersial, tidak ada negara Muslim merdeka yang diketahui eksistensinya dimana pun di sebelah Timur Samudera sebelum pertengahan abad keempat belas.[20] Di Samudera Pasai bertemu dengan salah seorang perwira tinggi militer, yang ternyata sudah dikenalnya. Orang itu pernah berpergian ke Delhi beberapa tahun sebelumnya dalam rangka misi diplomatik bagi Samudera.[21]
Setelah Kerajaan Samudera Pasai di Aceh tepatnya di Pidie ditemukan Kerajaan Islam Lamuri. Meski masih simpang siur, kabar tentang kerajaan ini, berdasarkan penulis-penulis luar, kerajaan Lamuri sudah disebut-sebut oleh berita-berita Arab sejak pertengahan abad ke IX M. Seperti juga kerajaan Islam Sumadra Pasai yang berpola maritim dan Islam, maka kerajaan Lamuri yang juga hampir berpola sama tentunya juga mempunyai sistem dan lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan kerajaan Islam Samudra Pasai.[22]
Terakhir, kerajaan Islam yang sampai sekarang masih dikaji adalah Kerajaan Islam Aceh. Pusat Kerajaan Aceh itu di Banda Aceh atau di Kutaraja sekarang ini yang mulai didirikan pada abd ke XV. Pada mulanya pusat pemerintahan Aceh terletak di satu tempat yang dinamakan kampung Ramni dan dipindahkan ke Darul Kamal oleh Sultan Alaudin Inayat Johan Syah (1408-1465) Kemudian memerintah Sulthan Muzaffar Syah (1465-1497. Beliaulah yang membangun kota Aceh Darussalam.[23]
Dari paparan di atas, yang ingin dikatakan bahwa bangsa Aceh telah lama menjadi bagian tersendiri dari kepulauan Nusantara. Walaupun demikian, jika data historis ini ditampilkan lagi sekarang, apakah bangsa Aceh akan bangkit seperti dulu lagi. Atau, sebaliknya justru malah mengalami kemunduran yang lebih parah dari sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pada bagian selanjutnya akan diulas tentang perkembangan ilmu pengetahuan di Aceh. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk membandingkan semangat pencarian ilmu tempoe doeloe dengan sekarang.
2. Ilmu Pengetahuan
Sayang memang, daerah Aceh sekarang menjadi propinsi terbelakang dalam bidang pendidikan. Daerah ini dulunya menjadi tempat mencari ilmu pengetahuan, sekarang malah sebaliknya, dari Aceh banyak yang mencari ilmu ke luar daerah yang pada gilirannya mutu pendidikan di daerah semakin menurun drastis. Bagi kita, khsusunya penulis, pendidikan adalah bentuk perjuangan total masa sekarang dan yang akan datang di Aceh.
Bangsa Aceh telah lama menjadi pusat pengkajian ilmu pengetahuan, khususnya studi Islam (islamic studies). Hampir setiap Raja di Aceh didampingi oleh para alim ulama. Di samping itu, lembaga pendidikan dayah[24] juga dapat ditemui di hampir seluruh daerah Aceh. Dayah di Aceh berfungsi 1) sebagai pusat belajar agama; (2) benteng terhadap kekuatan melawan penetrasi penjajah; (3) agen pembangunan; (4) sekolah bagi masyarakat.[25]
Oleh karena itu, tidak heran jika lembaga ini di Aceh menjadi pusat penggerak rakyat dalam berbagai bidang. Sebagai pusat belajar agama, dayah telah mendidik para calon ulama yang sampai sekarang masih dapat dilihat ditengah-tengah masyarakat. Menurut sejarah, para ulama yang datang dari Timur Tengah mengajarkan ilmu agama Islam di dayah-dayah. Atau, para teungku dayah pernah belajar pada seorang alim ulama dari Timur Tengah. Sebagai benteng pertahanan, dayah telah menoreh catatan sejarah tersendiri dalam lintasan berbagai peristiwa di Aceh. Bahkan pada waktu Kesultanan Aceh diserang Belanda, para ulama dengan gigih bertahan.[26]
Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dayah memegang peran yang cukup signifikan di Aceh. Jadi, jangan heran, jika sekarang ulama dan dayah di Aceh sering menjadi basis pertahanan Gerakan Acheh Merdeka. Hemat penulis, mereka mencontoh sejarah tempoe doeloe.
Selain dayah, di Aceh juga sangat terkenal dengan ulama yang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, khususnya Islam. Nama seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Abdur Rauf Singkeli, Nurdin Al-Raniri merupakan ulama yang sangat produktif menulis.[27] Melalui karya-karya mereka, Aceh dikenal sebagai tempat untuk mencari ilmu pengetahuan. Syekh Burhanuddin dari Ulakan, Pariaman adalah salah seorang ulama yang pernah belajar di Aceh. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pusat pencerahan ilmu pengetahuan di Indonesia di mulai dari Aceh.[28]
Kenyataan sejarah tersebut memang diakui oleh para peneliti sejarah. Namun sayangnya, sejarah tersebut tidak dapat diulangi oleh generasi selanjutnya. Setelah kedatangan Belanda dan diteruskan oleh pergolakan demi pergolakan di Aceh telah menyebabkan pencarian ilmu pengetahuan di Aceh mengalami kemunduran pada titik nol. Hal ini memang sangat berlebihan, tapi jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, kontribusi generasi Aceh terhadap peningkatan ilmu pengetahuan di Aceh sangat lamban. Hal ini disebabkan oleh gejolak di Aceh semenjak pasca kemerdekaan sampai dengan sekarang ini.
3. Agama
Di Aceh, agama (baca: Islam) menjadi sendi pokok dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua lapisan masyarakat selalu melandaskan pada agama Islam. Sehingga, kekuataan agama menjadi salah satu pendorong dalam perjuangan bangsa Aceh. Melalui agama, kerajaan juga bisa berkembang. Lewat agama juga, ilmu pengetahuan bisa mencapai kemajuan yang sangat berarti. Demikian, juga agama menjadi hukum bagi masyarakat Aceh.
Sebagai contoh, dua aspek di atas yaitu politik dan ilmu pengetahuan selalu mengedepankan Islam sebagai landasannya. Undang-undang Kerajaan Aceh hampir semuanya berdasarkan pada agama.[29] Untuk mengambarkan data sejarah yang nyata tentang peran agama di Aceh, dalam manuskrip kitab Tazkirah Thâbaqat Jumû‘ Sultân As-Salâtîn disebutkan bahwa:
“Syahdan ( ) maka ketahui oleh hai talib bahwa pada negeri Islam dalam seluruh dunia ini dari dahulu sampai sekarang hingga akan datang tiap-tiap kerajaan ( ) Islam hendaklah memegang tiga perkara pertama qanun syara‘ Allah kedua qanun syara‘ Rasul Allah ketiga qanun syara‘ kerajaan maka tiga macam ( ) seperti yang tersebut maka hendaklah memegang oleh sulthan-sulthan dengan teguh supaya negeri aman dan rakyat senang hidup dengan makmur ( ) wajib itu dua macam yang pertama wajib fardhu ain yang kedua wajib fardhu kifayah”.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa agama merupakan tiang pokok masyarakat Aceh. Karena itu, dengan semangat agama, semua persoalan di Aceh dapat diselesaikan. Dalam melawan penjajah, rakyat Aceh selalu melibatkan “agama di depan”. Tujuan yang hendak dicapai oleh agama adalah syahid.[30] Dan jika sudah syahid maka syurga adalah impian terakhir. Akibatnya, para syuhada di Aceh sangat banyak sekali. Ringkasnya, dengan ideologi jihad, kedatangan penjajah Belanda, menurut Azyumardi Azra, menjadi semacam “ rahmat terselubung”, bagi kelompok-kelompok etnis Muslim di kawasan ini.[31]
Pada saat yang sama, persoalan di Aceh juga selalu melibatkan agama. Misalnya, Gerakan Di/TII yang dipelopori oleh Daud Beureueh dalam Manifesto Pemberontak Aceh juga mengatasnamakan agama sebagai alasan gerakan tersebut. Untuk lebih lengkapnya mengenai teks manifesto tersebut, kami sebutkan di bawah ini:
“Atas nama Allah kami rakyat Aceh sudah membuat sejarah baru di atas persada tanah tumpah darah, kami berkehendak membentuk suatu Negara Islam.
Kami telah jemu melihat perkembangan-perkembangan atas dasar Negara Republik Indonesia, betapa tidak, sejak dahulu kami berharap, bercita-bercita negara berkisar atas dasar Islam, akan tetapi jangankan terujud apa yang kami idam-idamkan, malahan sebaliknya semakin hari tampak pada kami ada di antara pemuka-pemuka Indonesia mencoba membelok ke arah yang sesat.
… Jika pidana Tuhan tidak berlaku, itu berarti menyimpang dari Ketuhanan Yang Maha Esa.
Andaikan Undang-Undang Dasar R.I. sudah memberi jaminan kemerdekaan beragama c.q. Islam, sudah lama pula dapat berjalan hukum-hukum agama di tanah Aceh, yang rakyatnya 100 persen beragama Islam.
Malahan oleh Kejaksaan Agung sendiri pernah mencoba-coba mengeluarkan berkhotbah di mesjid atau di tempat-tempat lain yang katanya tempat agama, yang berisi politik, padahal bagi kami politik ialah sebagian dari agama yang kami anut, kalau boleh kami mengatakan bahwa Kejaksaan Agung ialah instansi resmi yang mula-mula mencoba menghalangi-halangi kami beragama, yang harus diminta pertanggung jawaban di hadapan Undang-Undang Dasar Negara dan di depan Tuhan, jika orang dari Kejaksaan Agung juga beragama Islam dan beriman kepada Tuhan.
…. Rasa sedih dan kesal ini memupuk keinginan kami untuk membentuk suatu Negara Islam. Andaikata orang menyalahkan kami, maka kesalahan itu harus mula-mulanya ditimpakan kepada pundak Sukarno sendiri.
Andaikata orang mengatakan pembentukan Negara Islam di Aceh berlawanan dengan hukum dan mengakibatkan kekacauan, kami akan mengatakan bahwa tindakan kami ini disebabkan oleh hukum yang kacau atau karena kekacauan hukum; tentu tidak heran; kekacauan akibat (karena) kekacauan hukum, tentu orang tidak dapat memperbaiki akibat sebelum ia sendiri memperbaiki asal pokok musababnya….”[32]
Jadi, di Aceh agama dijadikan standar dalam segala sisi kehidupannya. Jika sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan agama, maka hal tersebut tidak akan dipermasalahkan. Begitu juga sebaliknya, jika ada masalah bertentangan dengan agama, maka nyawa sebagai taruhannya. Untuk itu, sejarah telah membuktikannya.
Pantulan Sejarah Terhadap Persoalan Aceh Sekarang
Dari uraian sejarah di atas, tampaknya gejolak di Aceh tidak lepas dari konteks sejarah. Karenanya, untuk menganalisa masalah Aceh, berikut ini akan diketengahkah beberapa titik balik sejarah Aceh yang sedikit banyak mengalami paradoks.
a) Setelah melihat kekuatan politik Aceh tempoe doeloe, maka hal yang pertama yang terjadi di Aceh adalah merosotnya kekuataan politik di Aceh, baik itu di kalangan rakyat baik di dalam maupun di luar Aceh. Dahulu, persatuan kerajaan Islam Aceh telah menyebabkan daerah ini mampu menguasai sampai ke Semenanjung Malaka. Sekarang setelah tidak adanya persatuan politik tentang kesadaran akan sebagai rakyat Aceh, persoalan yang terjadi tidak pernah terselesaikan. Indikasi yang menunjukkan ke arah tersebut nyata di depan mata. Dulu, rakyat Aceh mendapat bantuan dari berbagai kerajaan (negara) Islam. Sekarang setelah kekuatan politik lemah, tidak ada satu negara pun yang membantu Aceh.
Selain indikasi di atas, rakyat Aceh tidak pernah bersatu dalam satu ikatan. Dalam konteks ini, istilah lain adalah pengkhianat. Hampir seluruh perjuangan bangsa Aceh kandas di tangan pengkhianat. Para syuhada, kecuali gugur secara wajar, banyak juga yang wafat karena ulah pengkhianat. Watak ini sampai sekarang masih membekas. Para pengkhianat ini selalu melintasi sejarah Aceh.[33] Mereka terkadang secara terang-terangan menjual Aceh kepada penjajah atau juga dengan cara diam-diam. Adanya pengkhianat ini telah mengkandaskan perjuangan bangsa Aceh sejak zaman Belanda. Sejauh pengetahuan penulis, Teuku Chik Di Tiro meninggal setelah diracuni oleh seorang janda. Cut Nyak Dhien ditawan oleh Belanda karena diberitahu oleh salah seorang kawannya. Masih banyak bentuk pengkhianatan lain yang sampai sekarang membekas dalam benak rakyat Aceh.
Selain pengkhianatan, di Aceh juga terjadi “dendam sejarah” yang sampai sekarang masih api dalam sekam. Akibat dari “dendam sejarah”, tidak heran jika ada segolongan rakyat Aceh tidak punya keinginan menyelesaikan kasus Aceh. “Dendam sejarah” tersebut adalah “Peristiwa Cumbok”. Peristiwa ini, menurut Taufik Abdullah, “revolusi sosial” di Aceh. Inti dari “revolusi” tersebut banyak uleebalang yang menemui ajalnya, dan banyak pula harta mereka yang dirampas.[34] Efek dari peristiwa tersebut telah menyebabkan rasa persatuan di kalangan rakyat Aceh melentur sehingga sangat mudah dimasuki oleh “penjajah” model baru. “Penjajah” ini sangat paham akan kekuatan rakyat Aceh, sehingga yang pertama kali dikikis habis adalah rasa “memiliki” Aceh.
Orang Aceh Utara mengatakan bahwa dirinya adalah orang “paling” Aceh, sebab kawasan ini banyak industri vital. Begitu juga Aceh Pidie juga menyebutkan bahwa dirinya orang “paling” Aceh, karena dari daerahnya banyak muncul tokoh-tokoh penting dalam sejarah Aceh. Pada saat yang sama, orang Gayo yang tidak ingin disebut orang Aceh. Karenanya, mereka selalu menyebut dirinya “orang Gayo”.[35] Padahal dalam sejarah bangsa Aceh, persaingan tingkat inter-etnis lokal tidak pernah ada. Dahulu para pahlawan dalam bergerilya hampir menyisir seluruh bagian Aceh. Kenapa sekarang, ketika sudah merdeka kita membuat “kapling ideologi”. Sesungguhnya, hal tersebut tidak pernah terjadi dalam sejarah Aceh.
Kenyataan ini, adalah potensi yang menciptakan perpecahan di Aceh. Potensi tersebut dapat dibaca oleh “musuh” baik itu dari dalam maupun dari luar. Karenanya tidak heran jika sekarang peta pergerakan perjuangan di Aceh sangat beragam. Di tingkat lapangan ditemui GAM dengan rakyat. Di tingkat menengah dijumpai para mahasiswa dan aktivis LSM yang mempunyai beragam orientasi tentang persoalan Aceh. Di tingkat atas, para elit politik yang “bermain” di Jakarta, Aceh dan luar negeri.
GAM cenderung mendekati rakyat dengan pendekatan sejarah. Belum lagi persoalan GAM Cantoi[36] yang memeras rakyat. Di sini membuktikan rakyat Aceh belum matang dalam mempelajari politik. Memang jika semua kita membenarkan gerakan kita atas nama sejarah, maka sejarah yang mana yang kita harapkan dari masyarakat. Mengapa sejarah tersebut tidak dijadikan sebagai pusat kesadaran kolektif masyarakat. Maksudnya, jika menurut sejarah, bangsa Aceh berhasil mengapa keberhasilan tersebut tidak kita contoh. Apakah sejarah hanya untuk membangkitkan semangat tanpa program dan target yang nyata.
Hal yang sama juga terjadi pada para mahasiswa penggagas Referendum, yang menurut hemat penulis telah tidak bertanggung jawab dalam menggulirkan isu tersebut. Awalnya, isu tersebut bisa menjadi pendidikan politik masyarakat Aceh. Sayangnya istilah tersebut diartikan dengan merdeka. Kekeliruan ini tentunya dimanfaatkan oleh kalangan yang menginginkan Aceh tetap kacau. Secara istilah, referendum adalah penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka menentukan (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat). Dalam hal ini, referendum ada dua yaitu referendum fakultatif tidak wajib meminta pendapat secara langsung (bergantung pada putusan penguasa), misal penetapan undang-undang; referendum obligator kewajiban meminta pendapat rakyat secara langsung dalam mengubah sesuatu, misal perubahan konstitusional.[37] Dalam konteks tersebut, nampaknya sosialisasi referendum di Aceh telah mengalami kegagalan sehingga yang ditengarai oleh Jeda Kemanusiaan yang secara hukum tidak mengakhiri proses pembantaian di Aceh. Sekali lagi, kalangan yang mensosialisasikan referendum telah terjebak ke dalam makna “merdeka” sehingga rakyat mengharapkan referendum yang oleh mahasiswa sampai saat ini belum bisa direalisasikan. Namun demikian, usaha ke arah tersebut patut dihargai meskipun dengan beberapa catatan di atas.
Adapun para elit politik dapat dibagi ke dalam empat golongan.
Pertama, mendukung sepenuhnya dan secara lantang mensuarakan kehendak rakyat Aceh. Namun terkadang usaha mereka kandas di tengah jalan. Ada yang diculik, dibunuh dan dibantai. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah Aceh tidak pernah terselesaikan.
Kedua, mendukung tapi tidak memperlihatkan dukungannya. Biasanya dukungan tersebut muncul ketika menyimak berita tentang Aceh. Kelompok ini biasanya sangat dekat dengan orang Aceh, tapi tidak punya “kuasa” dalam pengambilan keputusan politik.
Ketiga, tidak mendukung sepenuhnya. Kalangan ini secara terang-terangan memperlihatkan ketidaksukaan pada rakyat Aceh. Mereka ada yang terdiri dari orang Aceh dan bukan orang Aceh. Orang Aceh yang dimaksud adalah mereka yang punya “dendam sejarah” dan telah menikmati hasil keringatnya yang tidak mau “diganggu”. Sedangkan orang luar Aceh merupakan orang-orang yang punya kepentingan di Aceh baik secara politik maupun ekonomi. Nampaknya faktor terakhir lebih dominan ketimbang faktor pertama.
Keempat, tidak mendukung penyelesaian kasus Aceh, namun tidak memperlihatkan ketidakinginannya. Mereka cenderung bermain di belakang layar. Tujuan yang hendak dicapai, adalah sama dengan kelompok ketiga, tapi mereka punya pilihan lain jika keinginan mereka tidak tercapai. Atau dengan kata lain, jika perjuangan rakyat Aceh berhasil, maka mereka akan ke pilihan lain.
b) Pendidikan Aceh telah merosot ke titik nadir. Dulu Aceh menjadi pusat studi di Asia Tenggara. Sekarang, malah sebaliknya, kita orang Aceh “hengkang” dari Aceh ke luar Aceh dan mutu pendidikannya sangat rendah. Di tambah lagi mutu SDM kita sangat rendah. Akibatnya, dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang tinggi tidak didukung oleh SDM yang memadai yang akhirnya hasil-hasil bumi Aceh banyak dinikmati oleh non-bangsa Aceh.
Hemat penulis, kekuatan pendidikan di Aceh, sekarang ini banyak dikikis habis. Bukti konkret adalah pembakaran sekolah-sekolah dan sibuknya mahasiswa Aceh dalam gejolak di Aceh. Sehingga dapat dibayangkan, satu generasi Aceh akan bodoh total. Ramalan ini bukan mengada-ada. Jika usia 7 tahun (2000) tidak sekolah atau tidak ada keamanan, maka umur 25 tahun (2018) sebagai usia produktif akan berkurang mutu pendidikan di Aceh. Bisa dibayangkan bagaimana sejarah masa depan Aceh nantinya. Semua aspek kehidupan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan rakyat. Andai sejarah masa depan menjadikan bangsa Aceh merdeka, satu pertanyaan yang mungkin muncul yaitu bagaimana mutu pendidikan bangsa Aceh. Kita tentunya tidak ingin seperti Timor Timur. Begitu juga jika diberlakukan otonomi khusus, apakah bangsa Aceh siap mengelola hasil-hasil buminya.
Keraguan ini bukan tanpa alasan mengingat seluruh lapisan masyarakat Aceh telah melupakan pendidikan. Hampir semua bangsa Aceh melupakan faktor pendidikan, khususnya bagi generasi muda. Begitu juga, jika semua pemuda Aceh memanggul senjata atau demontrasi maka dapat dibayangkan pada tahun 2015, posisi Aceh dalam percaturan ilmu pengetahuan akan mundur ke belakang. Untuk itu, perlu dikembangkan lagi wajib belajar bagi mereka dan mau kembali membangun Aceh.
Kenyataan bahwa di Aceh terjadi pembodohan besar-besaran adalah bukan hal yang mesti dipungkiri. Sebab, cara pembodohan tersebut di Aceh sangat sistematis dan ini harus disadari oleh kita. Cara-cara tersebut adalah dengan membakar sekolah-sekolah, membantai para ulama,[38] dan membuat ketegangan di tengah-tengah masyarakat Aceh. Menurut sejarah, hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh Belanda ketika menjajah Aceh. Misalnya, dayah dibakar berikut kitab-kitabnya, ulama dibantai, masyarakat dibuat resah. Dengan demikian, dibutuhkan kesiagaan penuh untuk membangkitkan kembali pendidikan di Aceh.
Jika hal di atas, tidak menjadi perhatian kita, maka perjuangan bangsa Aceh akan sia-sia. Sebab, di era globalisasi yang akan berperan adalah teknologi dan ekonomi, di samping juga agama akan memegang peran yang signifikan.[39] Artinya, apabila bangsa Aceh ingin membuat sejarah lagi, maka tiga hal tersebut harus menjadi titik tekan dalam segala bentuk perjuangannya.
c) Agama tidak lagi menjadi perhatian dalam kehidupan di Aceh. Fenomena ini tidak sepenuhnya benar, namun arah kesana sudah nampak. Agama tidak lagi menjadi pertimbangan di Aceh. Nyawa, harta, wanita adalah hal yang biasa. Seorang yang membenci orang lain, nyawa adalah taruhannya. Hal ini memang telah terjadi sejak zaman penjajahan di Aceh. Dari waktu ke waktu, setiap nyawa pasti melayang di bumi ini. Bagi yang berjuang, nyawa adalah taruhan yang sangat cocok untuk mencapai kesyahidan. Dalam ini, agama adalah landasan. Tapi, bagi para “penjajah” nyawa adalah salah satu dari bentuk ”komando” yang harus dipatuhi.
Memang di Aceh akan berlakukan otonomi khusus yang diterjemahkan dengan semua urusan kecuali tiga urusan, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan (keluar) dan moneter, diserahkan kepada Daerah (selanjutnya disebut Nanggrau Aceh Darussalam – NAD). Atau dalam bahasa Dzulkarnain Amin, Aceh memperoleh “kemerdekaan ke dalam”.[40]
Dengan demikian, peran agama akan sangat menentukan tentang bagaimana aplikasi dari otonomi khusus. Untuk itu, ulama, umara dan rakyat Aceh sejatinya menjadikan agama sebagai landasan dalam pelaksanaan otonomi tersebut. Namun kendala muncul lagi yaitu bagaimana menerapkan agama dalam masyarakat yang sudah terkena “sindrom militerisme”. Istilah ini sengaja kami angkat guna memperlihatkan bahwa di Aceh sekarang gejala militerisme banyak ditemukan. Maraknya penghilangan nyawa secara paksa dan penyebaran fitnah adalah salah satu fenomena yang banyak ditemui di Aceh. Akhirnya, posisi agama akan sangat dilematis yang pada gilirannya penerapan agama ( baca: hukum) di Aceh akan menemui jalan buntu. Sebab, untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan undang-undang yang konon berita yang diterima RUU No.44 tahun 1999 belum disahkan sampai tulisan ini disampaikan.[41]
Jika RUU tersebut disahkan, maka perjuangan bangsa Aceh akan berhasil, namun jika tidak, perjuangan bangsa Aceh akan menebarkan sebanyak mungkin kehilangan nyawa dan fitnah. Dengan perkataan lain, “jalan buntu” di atas harus dicari “jalan alternatif” yaitu kemauan politik (political will) dari lima komponen perjuangan bangsa Aceh di atas (GAM, rakyat, mahasiswa, LSM, dan elit politik Aceh). Kelima komponen tersebut, sejatinya duduk dalam “satu meja” bermusyawarah bukan malah menciptakan konflik yang sama sekali merugikan masing-masing pihak.
Manakala hal tersebut terjadi, memori sejarah perjuangan bangsa Aceh tentang keserasian antara ulama, umara dan rakyat di Aceh akan terulang kembali. Kita mungkin masih ingat ketika perjuangan bangsa Aceh melawan Belanda dimana cara Belanda dalam menaklukan Aceh adalah dengan cara memecah belah bangsa Aceh, gambaran ini dapat diringkas sebagai berikut:
“Dalam usaha mereka untuk menguasai Aceh, Belanda mencoba untuk memisahkan kekuatan-kekuatan tradisional –sultan, uleebalang, dan ulama- dengan menawarkan “pemerintahan sendiri” (“self governing”) bagi para uleebalang dengan cara korteverklaring (deklarasi singkat) pada tahun 1874. Cara ini menghasilkan hubungan yang tidak harmonis antara uleebalang dan ulama, yang akhirnya terjadi konflik berdarah di antara mereka selang beberapa waktu setelah Indonesia merdeka pada 1945. Pada dasarnya, perselisihan ini merupakan hasil rekayasa Belanda yang dianjurkan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad ini.”[42]
Akhirnya,
“Dengan cara-cara di atas, Belanda berhasil memecah belah persatuan rakyat Aceh, yang pada gilirannya menyebabkan adanya konflik yang berkelanjutan antara kelompok yang pro-sultan dan pro-uleebalang. Di antara para uleebalang, ada yang sudah mempersiapkan untuk merebut korteverklaring, dan ada juga beberapa yang masih setia pada sultan. Kendatipun demikian, sultan memperoleh dukungan yang sangat kuat dari ulama, hal mana sangat anti terhadap Belanda. Dengan begitu, mereka memimpin perlawanan terhadap mereka. Bersama dengan para aristokrat yang masih mendukung sultan, para ulama ikut perang yang dilandaskan pada ajaran agama. Dengan menggunakan strategi perang gerilya, mereka terus-menerus berjuang dalam beberapa tahun untuk menghalangi Belanda yang membawa agama dalam kontrol mereka selama sepuluh tahun setelah sultan ditawan. Dengan demikian, Belanda tidak berhasil memerintah di Aceh sampai akhir tahun 1918, selama 45 tahun setelah meletus berperang.”[43]
Demikianlah yang dilakukan oleh Belanda dan nampaknya apa yang terjadi sekarang di Aceh tidak jauh berbeda dengan ilustrasi di atas. Teori Snouck dipraktekkan secara sistematis namun agak sedikit kejam, khususnya dalam bidang agama. Bukan maksud untuk membangkitkan rasa kemarahan, tragedi penerapan DOM di Aceh adalah bukti sejarah hitam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini, korban nyawa, harta, “perawan” (baca: pemerkosaan) adalah catatan pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum ada satu pun disidangkan menurut hukum negara Indonesia atau hukum Islam.
Setidaknya, menurut laporan catatan berbagai sumber, catatan pelanggaran HAM di Aceh sebagai berikut: Versi FP HAM 25 Kasus Tersadis. 1) Tak boleh tutup aurat saat shalat; 2) digorok dan rumah korban dibakar; 3) rumah terbakar, tak diganti rugi; 4) diikat, ditarik ramai-ramai, lalu didor; 5) diganduli batu, lalu dibenam ke sungai; 6) ajimat dicabut dan disiksa; 7) ditembak, kemudian kuburnya dibongkar; 8) digebuk, dicampak ke mobil, lalu dikubur massal; 9) ditembak di depan umum; 10) diciduk di masjid, dibantai di lapangan; 11) dijadikan tameng saat bertempur lawan GPK; 12) tangan dibedah, ditetesi air asam; 13) disiksa hingga mata kiri tak berfungsi; 14) diculik serempak lalu dibunuh massal; 15) santri diculik, lalu dibantai; 16) kepala dikuliti depan anak; 17) ditembak dalam sumur; 18) ditaruh pemberat besi; 19) disiksa sembilan malam, dilapari; 20) suami dibuang, istri disentrum: 21) semua gigi dirontokkan; 22) cacat karena dipukul dengan balok; 23) tulang rusuk dipatahkan; 24) digantung, kepala ke bawah; 25) diperkosa, hamil, ditinggal.[44]
Menurut versi AGAM, ada dua belas cara penganiayaan yang terjadi di Aceh terhadap tahanan selama DOM sebagai berikut: 1) disepak dan diterjang di bagian yang lemah dengan tujuan mencederakan; 2) pelir tahanan dijepit hancur dengan menggunakan tang; 3) Kaki kursi diletakkan ke atas anak jari kaki tahanan itu, kemudian para tentara duduk di atasnya untuk menambahkan tekanan atas anak kaki mereka sampai remuk–redam hancur berdarah; 4) telapak tangan dan kaki tahanan dipaku seperti orang yang disalin, hanya tiang salibnya saja yang tidak digunakan; 5) tahanan-tahanan direbus dengan air panas; 6) tahanan direndamkan berhari-hari atau berminggu-minggu dalam kolam air najis; 7) tahanan digantung kepala ke bawah dan kaki ke atas; 8) tubuh tahanan ditonjok dengan puntung rokok dan besi panas; 9) tahanan dipukuli dengan batang besi atau tangkai-tangkai yang keras berlapiskan papan tipis (triplek) di antara senjata tajam dengan tubuhnya supaya bila dipukuli tinggal bekas tetapi rusak di dalam badan tersebut semakin parah, sehingga mereka muntah darah; 10) kawat besi yang tajam dimasukkan ke dalam saluran kencing kemaluan kemudian diputar-putar kawat itu sehingga mengakibatkan sakit yang tidak terhingga; 11) tahanan-tahanan diikat ke sebuah balok es 1,5 meter, yang berjam-jam lamanya baru cair. Begitu mencair es batu tersebut, tahanan tersebut menjadi dan sudah tidak sadarkan diri; 12) ada di antaranya yang dicungkil matanya.[45]
Adapun pelanggaran HAM terhadap perempuan adalah menarik untuk mengutip versi Al-Chaidar (Aceh Bersimbah Darah), dkk. ada 12 cara yaitu 1) wanita Aceh diperkosa tiga tentara; 2) pelecehan seksual terhadap kaum wanita; 3) diperkosa, hamil, lalu ditinggal begitu saja; 4) gadis korban perkosaan melahirkan anak pemerkosa; 5) diperkosa sambil berdiri; 6) diperkosa, disetrum dan dicambuk dengan kabel; 7) ditelanjangi massal; 8) gadis cacat diperkosa oleh tentara yang sedang mabuk; 9)suami diculik, istri dilecehkan; 10) diambil paksa dan diperkosa; 11) diarak telanjang, lalu didor; 12) digagahi di depan anaknya.[46]
Data-data di atas adalah bukti nyata bahwa agama tidak lagi disegani oleh para pelanggar HAM. Ini membuktikan bahwa sebutan Serambi Mekkah tidak tepat lagi. Sebab jika yang namanya Mekkah, maka setiap darah di atas tempat tersebut adalah haram hukumnya kecuali murtad. Karena itu, sebutan “Serambi Mekkah” harus didefinisikan kembali dalam konteks ke-Aceh-an baru.
Paparan di atas merupakan pengingkaran sejarah bangsa Aceh terhadap apa yang sudah dibangun oleh para pendahulu ternyata disia-siakan. Dalam hal ini, ada pendapat yang menyebutkan mereka (para indatu kita) telah berjuang dan berkarya dengan baik sesuai dengan masanya. Kita tidak boleh bertepuk tangan atas kejayaan mereka, kita justru dituntut untuk berkarya sendiri.[47] Oleh karenanya tuntutan tersebut harus menjadi agenda kita semua sebagai generasi baru Aceh.
Dari paparan di atas ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Pertama, bahwa perjuangan bangsa Aceh merupakan tugas kita semua rakyat Aceh, tanpa kecuali. Oleh karena itu, skat-skat perbedaan antara kita seharusnya mulai di kikis. Dengan cara demikian, kajian sejarah di atas, merupakan salah satu pedoman dalam melakukan perjuangan.
Kedua, bentuk perjuangan dengan kesadaran sejarah adalah perjuangan yang menyeluruh. Maksudnya, perjuangan bangsa Aceh harus dilaksanakan secara kolektif tanpa ada pengembosan atau pengkhianat. Jika sejarah, membuktikan bahwa bangsa Aceh mampu mengusir penjajah, mengapa kita di era modern tidak mampu berbuat demikian. Dengan perkataan lain, perjuangan bangsa Aceh harus didefinisikan ulang yaitu perjuangan bangsa Aceh untuk golongan, kalangan atau demi tanah Rencong. Jika demi kalangan dan golongan, maka sampai kapanpun perjuangan bangsa Aceh akan tetap mengalami kegagalan. Namun jika perjuangan demi tanah pertiwi Aceh, maka Insya Allah bantuan akan datang seperti para indatu kita dulu berjuang.
Ketiga, khusus bagi generasi muda adalah bagaimana mempersiapkan Aceh di masa depan bukan malah terjebak pada permasalahan politik yang tidak jelas. Oleh karenanya, pendidikan merupakan salah satu persiapan untuk arah ke sana. Sebab untuk mengharapkan generasi sekarang berjuang demi Aceh adalah harapan yang berlebihan. Karena, perjuangan selalu membutuh waktu dan ruang. Mereka tentu telah berjasa dan pada saat yang sama Aceh juga masih menunggu jasa-jasa kita.
Akhirnya, saran saya kepada kita adalah mari kita membuat sejarah yang akan dibaca oleh cucu kita sebagaimana kita membaca sejarah nenek moyang kita. Sebab walau bagaimanapun sejarah adalah cermin suatu bangsa.
[1]H.M. Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961).
[2]Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah, (Jakarta: Sinar Harapan, 1987); idem, Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 1999).
[3]Lee Kam Hing, The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760-1824, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995).
[4]C. Snouck Hurgronje, Aceh: Rakyat dan adat Istiadatnya, 2 Jilid (Jakarta: INIS, 1997).
[5]Sejauh ini, meskipun bukan peneliti sejarah, penulis telah mengumpulkan beberapa literatur sejarah tentang Aceh yang ditulis oleh berbagai pihak. Untuk lebih mendalami dan mengerti sejarah Aceh, maka penulis menganjurkan untuk membaca beberapa karya berikut: Luthfi Auni, ”The Decline of The Islamic Empire of Aceh,” Tesis M.A. McGill University, (1993); Amirul Hadi, ”Aceh and The Portuguese: A Study of the Struggle of Islam in Southeast Asia 1500-1579,” Tesis M.A. McGill University, (1992); M. Hasbi Amiruddin, ”The Response of The Ulama Dayah to the Modernization of Islamic Law in Aceh,” Tesis M.A. McGill University, (1994); Hamdiah Latif, ”Persatuan Ulama Aceh (PUSA): Its Contribution to Educational Reforms in Aceh,” Tesis M.A, McGill University, (1992); Amran Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990). Namun dewasa ini, sejak pergolakan Aceh, sejarah Aceh juga masih ditulis. Baca misalnya, Al-Chaidar, dkk., Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) Di Aceh 1989-1998, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1999); Yusra Habib Abdul Ghani, Mengapa Sumatera Menggugat, (Biro Penerangan Acheh-Sumatera National Liberation Front, 2000); Fikar W. Eda dan S. Satya Dharma (peny.), Aceh Menggugat: Sepuluh Tahun Rakyat Aceh di Bawah Tekanan Militer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999); Kaoy Syah dan Lukman Hakiem, Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah: Proses Pembentukan UU No.44/1999, (Jakarta: Pengurus Besar Al-Jami’iyatul Washliyah, 2000).
[6]Kasus kongkret adalah apa yang dialami oleh bangsa Indonesia, menurut Asvi Warman Adam, pada masa awal Orde Baru, strategi pengendalian sejarah mencakup dua hal: pertama, mereduksi peran Soekarno, dan kedua, membesar-besarkan jasa Soeharto. Lihat Asvi Warman Adam, ”Pengendalian Sejarah Sejak Orde Baru,” dalam Henri Chambert-loir dan Hasan Muarif Ambary (ed.), Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 572.
[7]Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1996), 161.
[8]Asvi Warman Adam, Pengendalian Sejarah, 576.
[9]Sejauh pengetahuan penulis, pendekatan sejarah sering digunakan oleh Gerakan Acheh Merdeka dalam mensosialisasikan program-programnya. Lihat misalnya Tengku Hasan di Tiro,”Perkara & Alasan Perdjuangan Angkatan Atjèh Sumatera Merdéka”, Tjeramah :Dimuka Scandinavian Association of Southeast Asian Social Studies Göteborg, Sweden, 23 Agustus, 1985. Untuk membuktikan asumsi ini, penulis mengutip sepenggal ceramah Hasan Di Tiro,” Lama sekali sebelum kedatangan pendjadjahan2 Eropa Barat ke Dunia Melaju (Asia Tenggara) Atjeh sudah mendjadi satu negara merdeka jang berdaulat jang diakui dunia internasional di Sumatera. Pada waktu itu negara merdeka itu lebih terkenal dengan nama Keradjaan Atjeh, tetapi kemudian mendjadi lebih terkenal dengan nama sebuah pelabuhannja jang sering dikundjungi oleh kapal-kapal Eropa, jaitu pelabuhan ‘Samudra’ di Atjeh Utara, jang dari padanja berasal nama Sumatera. Buku Larouse Grand Dictionnaire Universelle, menggambarkan Keradjaan Atjeh pada waktu itu sebagai "bangsa jang paling berkuasa di Dunia Melaju atau Hindia Timur, pada achir abad ke-16 dan sampai pertengahan abad ke-17. ("Vers la fin du XVIe siècle et jusqu’ à la moitië du XVIIe, les Achins etaient la nation dominante de l’archipel Indien.") Vol.I, p.70, Paris, 1886. Sebuah sumber sedjarah jang besar jang lain, La Grand Encyclopedie, menulis sebagai berikut: "Pada tahun 1582, bansa Atjeh sudah meluaskan kekuasaannja atas pulau2 Sunda (Sumatera, Djawa, Borneo, dll), atas satu bagian dari semenandjung Tanah Melaju, dan mempunjai hubungan dengan segala bangsa jang melajari lautan Hindia, dari Djepang sampai ke Arab. Sedjarah peperangan jang lama sekali jang dilantjarkan oleh bangsa Atjeh terhadap bangsa Portugis jang menduduki Malaka sedjak permulaan abad ke-16, adalah halaman2 jang tidak kurang kemegahan dan kebesarannya dalam sedjarah bangsa Atjeh. Pada tahun 1586, seorang Sultan Atjeh menjerang Portugis di Malaka dengan sebuah armada yang tediri dari 500 buah kapal perang dan 60,000 tentera laut." ("En 1582, ils avaint étandu leur Malacca depuis le commentcement du XVIe siècle n’est pas une des pages les moins prépondérance sur les iles de la Sonde, sur une partie de la Presque ‘ile de Malacca, ils étaient en relation avec tous les pays que baigne l’océan Indien depuis le Japan jusqu´ à glorieuse de l’ histoire des Atchinois. En 1586, un de leur Sultans attaque les Portugais avec une flotte d’ environ 500 voiles montée par 60,000 marins." (Vol.IV,p.402, Paris,1874)”. Lihat juga “Pernjataan Atjeh Sumatera Merdeka Kembali,” oleh Tengku Hasan di Tiro, 4 Desember, 1976, dimuat dalam AGAM: Madjallah Angkatan Atjeh Meurdehka, No.40 (1991), 72-74; idem,”Nasionalisme Indonesia,” Suara Acheh Merdeka, edisi VI Desember (1995), 22-23. Tulisan ini kembali dimuat dalam Yusra Habib Abdul Ghani, Mengapa Sumatera Menggugat, 42-52. Lebih dari itu, Tengku Hasan Di Tiro, konon menurut kabar tersiar adalah Wali Negara Acheh Merdeka. Dia memilih dirinya sendiri sebagai wali negara. Berikut petikan salah satu tulisan Hasan Di Tiro, ”Saya telah menanda-tangani Surat Pernyataan Acheh/Sumatera Merdeka sebagai Negara Sambungan atas kelegalan Hak Successor State sebab pada waktu ini saya yang berhak (bertugas) sebagai Wali Negara Acheh sebagai Tengku Tjhik di Tiro menggantikan (cetak miring dari penulis) Yang Mulia Nenekanda Tengku Tjhik Mahyeddin dan Pamanda Tengku Tjhik Ma’at, yang gugur pada 3 Desember, 1991, dalam perang dengan Belanda.” Lihat Tengku Hasan Di Tiro,”Konsep-Konsep Ideologi Acheh Merdeka,” Suara Acheh Merdeka, (1995), 34. Untuk mengetahui latarbelakang mengapa Hasan di Tiro mendirikan organisasi Acheh Merdeka, baca Tengku Hasan di Tiro, The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro, (National Liberation Front of Acheh Sumatra, 1984).
[10]Penting dicatat bahwa pada saat kekuatan-kekuatan imperialis Barat telah mematahkan kekuatan sebagian besar negara-negara Islam, pada saat itulah, pada permulaan abad XVI, lahirlah “Lima Besar Islam” yang terikat dalam suatu kerjasama ekonomi, politik, militer dan kebudayaan. Lima Besar Islam yang dimaksud yaitu: 1. Kerajaan Turki Usmaniyah, yang berpusat di Istambul, 2. Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara, 3. Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, 4. Kerajaan Akra di India, 5. Kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara. Baca, Ali Hasjmy,”Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan,” dalam Ismail Suni (ed.), Bunga Rampai Tentang Aceh, 208.
[11]Asal kata Peureulak menurut Ali Hasjmy adalah sebagai berikut: di satu daerah di wilayah Aceh Timur sekarang, banyak sekali tumbuh kayu besar, yang bernama “Kayei Peureulak” (Kayu Perlak), bahkan telah merupakan “Rimba Peureulak”. Kayei tersebut sangat baik untuk bahan pembuatan perahu, kapal, sehingga banyak dibeli oleh perusahaan-perusahaan kapal/perahu.… Kemudian para pengembara/pedagang sebelum “Zaman Islam” yang datang dari Cina, Arab, Persia, Hindi, Italia, Portugis dan lain-lainnya melalui Selat Melaka dan singgah di Pelabuhan daerah Kayei Peureulak, terus menyebut pelabuhan yang mereka singgahi itu dengan “Bandar Perlak”. Lihat A. Hasjmy, ”Adakah Kerajaan Islam Perlak Negara Islam Pertama di Asia Tengara,” dalam A. Hasymy (ed.), Sejarah Masuk,